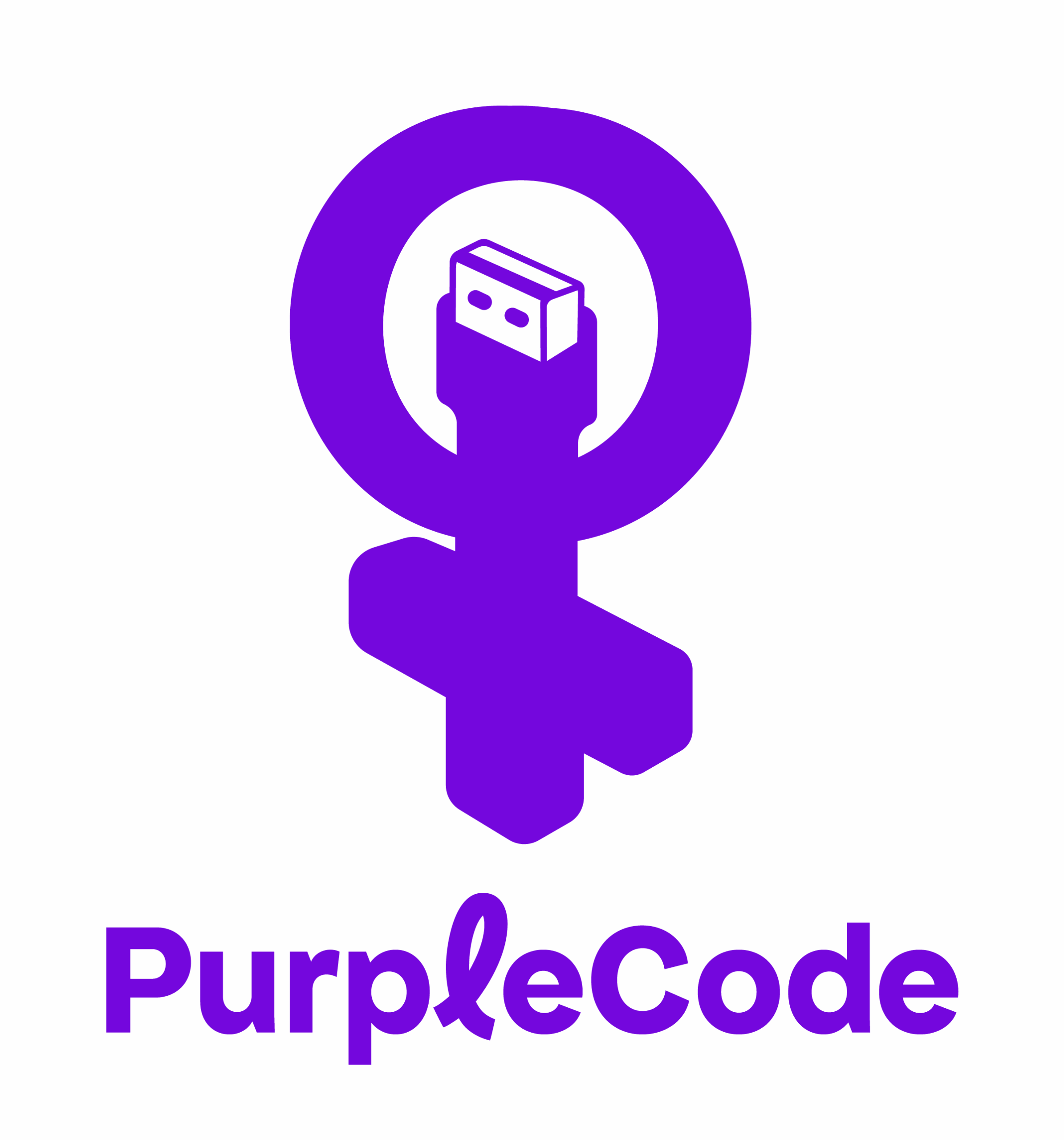Akhir Juni lalu, saya membuka Twitter dan menemukan cuitan terkait penyebaran Non-Consensual Dissemination of Intimate Image (NCII)—sayangnya, sampai sekarang masih dikenal sebagai revenge porn[1]—yang dialami oleh korban di Pandeglang, Banten. Saat itu saya hanya tahu bahwa kasus tersebut masuk dalam kualifikasi Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), dan belum membacanya secara detail.
Beberapa hari setelahnya, saya membaca rangkaian cuitan[2] yang dibuat oleh kakak korban. Berkali-kali saya mengernyitkan dahi melihat respons kejaksaan atas kasus ini. Suatu kali, Kejaksaan Negeri Pandeglang bahkan mengunggah foto korban saat menghadiri forum pelayanan hukum. Saya yakin foto tersebut diunggah tanpa persetujuan (consent), karena akhirnya kakak korban yang meminta foto tersebut dihapus dari akun Instagram Kejaksaan Negeri Pandeglang. Sungguh tidak memiliki sensitivitas dan keberpihakan terhadap korban. Kritik publik terhadap aparat penegak hukum atas penanganan kasus kekerasan seksual memang masih bejibun. Mereka, kita, dan semua masih harus belajar.
Kasus KBGO yang terjadi pada korban di Pandeglang ini telah diputus melalui Putusan No. 71/Pid.Sis/2023/PN Pdl. Majelis Hakim menilai perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar tindak pidana yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) UU ITE.[3] Dua pasal ini pada intinya menghukum orang yang menyebarkan informasi dan/atau dokumen bermuatan melanggar kesusilaan secara elektronik.
Saya sudah menduga pasal ini akan digunakan. Menurut saya, tidak salah bahwa pelaku telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal tersebut. Tapi, saya merasa bahwa dimensi terjadinya kekerasan seksual, KBGO, kurang dilihat oleh penegak hukum. Persoalannya tidak berhenti pada video seksual yang disebar, tetapi dimensi KBGO berupa adanya relasi kuasa, ketiadaan persetujuan (consent), kekerasan psikis, dan keberadaan sekstorsi[4] perlu dilihat, ditelisik, dan dipertimbangkan. Idealnya, UU TPKS[5] dapat digunakan dalam penanganan kasus KBGO di Pandeglang ini. Penggunaan UU TPKS sebagai basis penanganan, setidaknya lebih berperspektif korban: pemeriksaannya, alat buktinya, hingga pemberatan hukumannya.
Saat saya membuka Direktori Putusan Mahkamah Agung, cukup sulit menentukan kata kunci pencarian perkara yang berdimensi kasus KBGO. Mengingat, istilah KBGO atau istilah padanannya belum banyak dikenal oleh Mahkamah Agung, juga instansi penegak hukum lainnya. Saya memutuskan untuk mencari perkara yang mengandung unsur “Pasal 27 ayat (1) UU ITE,” dan saya menemukan beberapa. Saya berhasil mengakses Putusan No. 188/Pid.Sus/2017/PN Gto, Putusan 144/Pid.Sus/2019/PN Bna, Putusan 1990/Pid.Sus/2019/PN Plg, dan Putusan No. 140/Pid.Sus/2020/PN Smp, yang keseluruhannya menggunakan Pasal 27 ayat (1) UU ITE sebagai dasar dakwaan—beberapa ada yang dikombinasi dengan pasal dan ketentuan lain. Untuk kepentingan analisis selanjutnya, saya juga menambahkan Putusan No. 407/Pid.Sus/2021/PN Smn. Penambahan satu putusan ini penting, karena dimensi KBGO-nya kental sekali, namun jaksa dan hakim tidak berhasil melihat dan menganalisisnya.
Satu temuan yang juga ingin saya sampaikan di awal—yang selaras dengan temuan dari Catahu Komnas Perempuan 2022 dan Refleksi TaskForce KBGO 2022—bahwa betul dan nyata, pelaku kekerasan seksual tidak jarang adalah orang-orang terdekat korban. Dari lima putusan yang saya baca, semua KBGO dilakukan oleh mantan pasangan atau seorang yang memiliki hubungan romansa.
Dari kelima putusan yang saya baca, sebetulnya, kualifikasi jenis KBGO-nya sangat beragam. Namun sayang, jaksa dan hakim hanya menilai bahwa KBGO yang terjadi adalah “penyebaran foto/video yang bermuatan asusila”.[6] Setelah saya membaca putusan-putusan tersebut, saya menemukan KBGO berupa pengambilan foto tanpa persetujuan (consent), sebagaimana terjadi dalam Putusan 1990/Pid.Sus/2019/PN Plg. Saat itu, terdakwa dan korban melakukan telepon video (video call) seksual. Tanpa sepengetahuan korban, terdakwa mengambil tangkapan layar telepon video seksual korban—yang selanjutnya digunakan sebagai alat untuk memeras korban.
Saya juga menemukan KBGO berupa impersonasi.[7] Ini terjadi dalam Putusan No. 144/Pid.Sus.2019/PN Bna dan Putusan No. 1990/Pid.Sus/2019/PN Plg. Dalam Putusan No. 144/Pid.Sus.2019/PN Bna, terdakwa melakukan impersonasi dengan cara membuat akun Facebook yang seolah-olah milik korban. Melalui akun tersebut, terdakwa juga mengunggah foto-foto seksual korban, bahkan diikuti dengan kalimat-kalimat seksual pula. Hampir sama, terdakwa dalam Putusan No. 1990/Pid.Sus/2019/PN Plg juga melakukan impersonasi dengan membuat akun Facebook atas nama korban, juga menggunakan foto seksual korban sebagai profil.
Selain impersonasi, saya menemukan pula KBGO berupa pemerasan (extortion)[8] dalam Putusan 1990/Pid.Sus/2019/PN Plg dan Putusan No. 140/Pid.Sus/2020/PN Smp. Terdakwa dalam Putusan 1990/Pid.Sus/2019/PN Plg melakukan pemerasan berupa uang. Terdakwa mengaku sedang dalam perjalanan menuju alamat korban, juga mengaku akan membeli oleh-oleh, sehingga meminta uang dari korban. Korban mengirimkan uang Rp 400.000,- untuk pertama kalinya, lalu terdakwa meminta lagi sebesar Rp 300.000,- tetapi korban tidak mengirimkan. Terdakwa mengancam akan menyebarkan foto seksual korban jika korban tidak mengirim uang. Pada akhirnya, terdakwa tetap menyebarkan foto seksual korban. Pemerasan juga terjadi dalam Putusan No. 140/Pid.Sus/2020/PN Smp. Bedanya, terdakwa memeras dengan melakukan pemaksaan agar korban mau menerima terdakwa kembali sebagai pasangan. Korban tidak mau, dan terdakwa mengirimkan video seksual korban ke salah satu grup WhatsApp miliknya dan media sosial.
Saya juga mendapatkan temuan yang menyedihkan. Waktu itu, saya pertama kali tahu Putusan No. 407/Pid.Sus/2021/PN Smn melalui kawan di TaskForce KBGO. Putusan ini sudah cukup lama saya baca, jika dibanding putusan-putusan lainnya. Saat membaca, saya meyakini bahwa apa yang dialami oleh korban adalah KBGO. Terdakwa mengancam akan menyebarkan video/foto korban, jika korban tidak memenuhi permintaan terdakwa untuk bertemu. Korban juga mengalami pemerasan uang oleh terdakwa. Jika korban tidak mengirimkan, maka terdakwa akan menyebarkan video/foto seksual korban. Dalam kasus demikian, jaksa menggunakan dakwaan alternatif berupa Pasal 27 ayat (4) jo. Pasal 45 ayat (4) atau Pasal 29 jo. Pasal 45B UU ITE. Pasal tersebut pada intinya mengatur mengenai pemerasan dan/atau pengancaman serta ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Bagi saya, penggunaan pasal-pasal tersebut kurang sensitif terhadap korban. Apa yang dialami korban jelas berdimensi KBGO.
Ketidakberhasilan aparat penegak hukum, khususnya jaksa dan hakim, dalam melihat dimensi KBGO pada beberapa putusan di atas menjadikan saya cukup sedih. Saya melihat mereka tidak berperspektif korban. Fokusnya hanya sampai pada “penyebaran foto/video yang bermuatan asusila,” padahal apa yang dialami oleh korban adalah kekerasan seksual, KBGO. Dengan menyimplifikasi perkara, ini menjadikan pertimbangan-pertimbangan terkait gender, relasi kuasa, dan persetujuan (consent) hilang.
Kegagalan memahami perkara-perkara di atas sebagai perkara kekerasan seksual juga berdampak pada administrasi peradilan, seperti halnya penulisan putusan. Mengacu pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, perkara terkait dengan tindak pidana kesusilaan seharusnya mengaburkan identitas saksi korban dan saksi lainnya. Adanya keputusan ini, harus menjadi pedoman dalam pelindungan identitas korban KBGO kedepannya. Bukan seperti putusan-putusan yang telah saya baca sebelumnya, di mana empat dari lima putusan menampakkan dengan jelas nama-nama korban. Bahkan terdapat putusan yang dengan terang menuliskan nomor telepon dan alamat korban. Tentu, ini adalah ancaman lanjutan bagi korban.
UU TPKS, juga UU PDP,[9] kini telah disahkan. Sudah seharusnya penegak hukum belajar dan memperbarui pengetahuannya. Kasus-kasus KBGO sudah seharusnya diperiksa dengan metode-metode yang mengedepankan sensitivitas gender dan keberpihakan kepada korban.
————
[1] Istilah revenge porn tidak tepat karena memiliki beberapa persoalan. Pertama, kata revenge (balas dendam) seolah-olah mengarahkan orang untuk beranggapan bahwa korban telah melakukan sesuatu yang buruk sehingga pelaku layak melakukan perbuatan balas dendam. Padahal yang terjadi dalam KBGO tidak demikian. Kedua, kata porn (pornografi) merujuk pada materi visual privat yang diproduksi untuk tujuan hiburan dan konsumsi publik, yang mana semua tindakan seksual dilakukan dengan persetujuan (consent). Sedangkan, dalam KBGO, materi yang dibuat tidak dimaksudkan untuk hiburan maupun konsumsi publik. Lihat: PurpleCode Collective, Buku Saku #1: Mengenal Dasar-Dasar KBGO, PurpleCode Collective, https://web.tresorit.com/l/6BdDo#OD-9z2OdX0KP32wZIW2M9g, 2021, h. 28 – 29.
[2] @zanatul_91, Twitter, https://twitter.com/zanatul_91/status/1673188021519405056?s=46, diakses pada 3 Juli 2023.
[3] Pandeglang Eksis, Instagram, https://www.instagram.com/p/CuoLNvbLTBT/, diakses pada 13 Juli 2023.
[4] Sekstorsi adalah kekerasan berupa pemerasan yang melibatkan tindakan seksual. Ini bisa berupa hubungan seksual maupun repetisi pengiriman foto atau video intim/bernuansa seksual. Lihat: PurpleCode Collective, Buku Saku #1: Mengenal Dasar-Dasar KBGO, Op.Cit., h. 30.
[5] Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Melalui beberapa pasalnya, UU TPKS telah mengatur mengenai KBGO. Meskipun, istilah yang dipakai bukan KBGO tetapi Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE).
[6] Penggunaan terma ‘asusila’ sebenarnya tidak tepat. Terdapat setidaknya dua alasan mendasar yang menjadi basis argumen. Pertama, asusila secara bahasa dimaknai sebagai tingkah laku yang tidak baik (KBBI, 2023). Ini berarti mempersamakan posisi korban dan pelaku sebagai seseorang yang salah karena telah berperilaku tidak baik. Pemaknaan demikian, tentu mengaburkan tindakan kekerasan seksual yang dilakukan pelaku terhadap korban. Kedua, penggunaan terma asusila berarti mendegradasi kekerasan seksual sebagai sebuah perbuatan bukan pidana. Melainkan, sebatas tingkah laku tidak baik yang dilakukan oleh pelaku dan korban. Terma yang tepat menggantikan asusila adalah ‘kekerasan seksual’.
[7] Impersonasi adalah kekerasan berupa pembuatan akun/profil palsu oleh pelaku, yang seolah milik seseorang (korban), yang digunakan untuk mengunggah konten-konten ofensif, provokatif, subversif, ataupun seksual dengan tujuan merusak/mencemarkan nama baik dan memancing orang lain melakukan serangan bahkan kriminalisasi. Lihat: PurpleCode Collective, Buku Saku #1: Mengenal Dasar-Dasar KBGO, Op.Cit, h. 34.
[8] Pemerasan (extortion) adalah kekerasan berupa ancaman dalam bentuk apapun untuk membuat korban melakukan apa yang diinginkan oleh pelaku. Apabila pelaku adalah mantan pasangan, bentuk pemerasannya bisa berupa pemaksaan agar korban mau menerimanya kembali dengan semua kondisi kekerasan yang menyertai. Dalam sejumlah kasus, pemerasan juga bisa dilakukan untuk meminta uang. Lihat: PurpleCode Collective, Buku Saku #1: Mengenal Dasar-Dasar KBGO, Op.Cit, h. 29.
[9] Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.