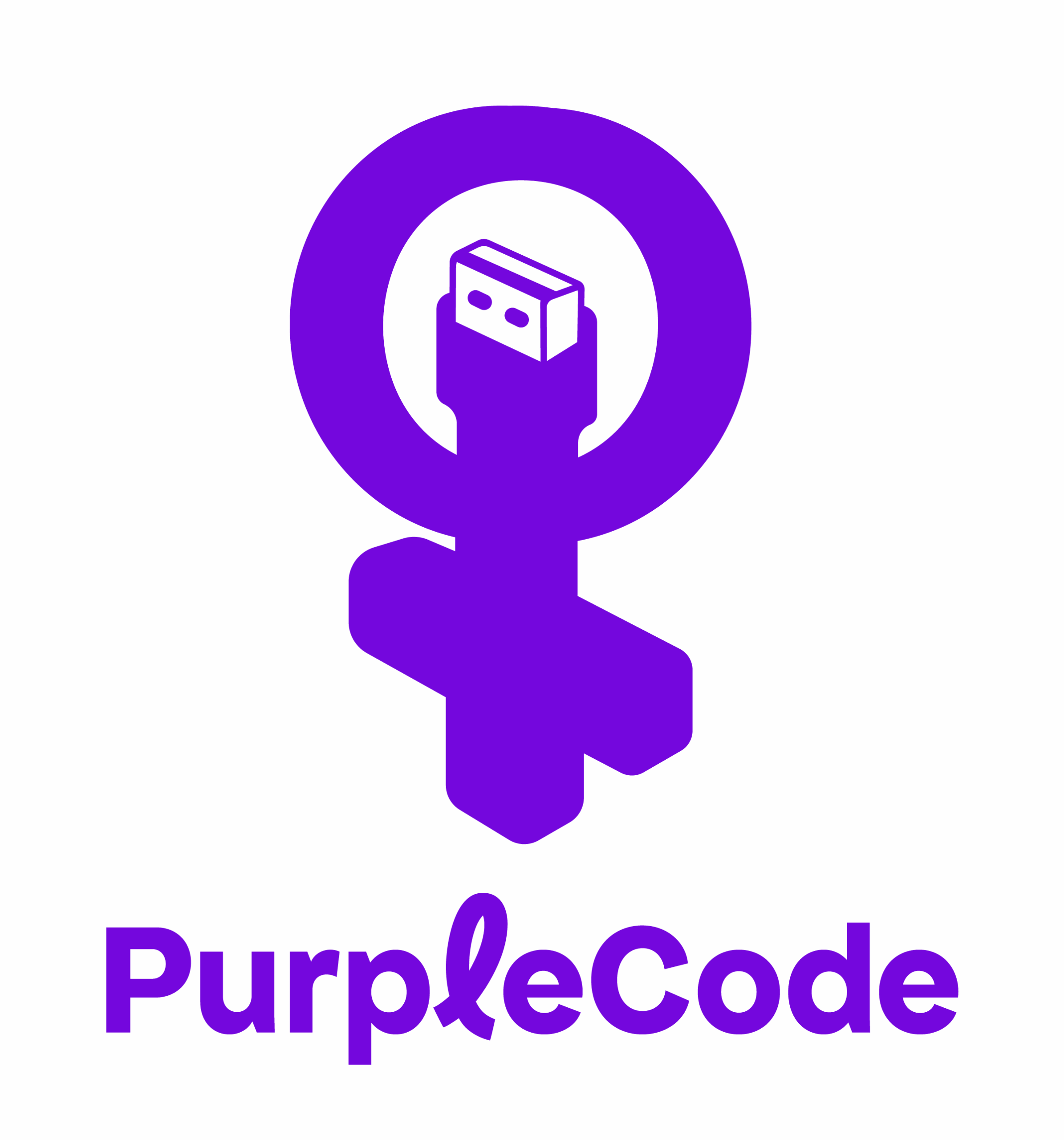Baru-baru ini, orang terdekatku dikejutkan oleh sebuah notifikasi yang muncul dari akun Twitter nya (sekarang X). Ia memberitahu bahwa keponakannya yang duduk di bangku SD baru saja mengikuti (follow) akun Twitter nya. Syukurnya hal ini dengan sepengetahuan dan supervisi orang tua. Tapi aku jadi bertanya-tanya, berapa banyak orang tua lain yang melek digital dan mampu mendampingi anaknya beraktivitas online?
Membicarakan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dan korban anak sebenarnya tidak mudah buatku. Ada dua hal yang sudah duluan membuatku ciut, bahkan sebelum membuat tulisan ini. Pertama, statusku yang tidak punya anak. Seringkali dikerdilkan dengan sahutan “Tau apa kamu soal…” Kedua, soal betapa kompleksnya kaitan anak, orang tua atau wali nya, dan literasi digital di Indonesia. Namun, pandangan yang coba aku tawarkan di sini berangkat dari satu, pengalamanku dulu sebagai seorang anak, dua, pengalamanku sebagai pendamping korban.
Setelah dua tahun berjalan bersama Task Force KBGO, rasanya ini saat yang tepat untuk memberi fokus lebih pada kasus-kasus KBGO yang dialami oleh korban berusia anak. Untuk menyamakan persepsi, anak yang kusebut di sini adalah mereka yang berusia kurang dari 18 tahun. Hal ini merujuk pada definisi yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak[1]. Tahun lalu, beberapa kali aku dan tim Task Force KBGO lainnya mendampingi korban yang masuk kategori remaja. Kanal aduan kami mengategorikan pengirim aduan menjadi dua, yaitu korban langsung, ataupun pendamping korban. Dalam catatan sepanjang tahun 2022[2], terdapat 12 anak yang mengidentifikasikan dirinya sebagai korban KBGO dan berani melapor. Dari total angka itu, 3 anak berusia 14 tahun, 3 anak berusia 16 tahun, dan 6 anak berusia 17 tahun.
Sebagian besar anak yang kutemani mengalami NCII (Non Consensual Dissemination of Intimate Images) atau penyebaran konten intim nonkonsensual). Tidak serta merta mereka menyebut istilah ini. Jenis KBGO ini kami petakan saat melakukan asesmen bersama korban dan/atau pendampingnya. Anak-anak perempuan ini mendeskripsikannya dengan: “Aku punya pacar, (atau) aku kenalan dengan seseorang secara online, lalu kami merekam, (atau) aku gak tau kalau aku direkam. Sekarang dia ancam aku bilang akan sebarkan foto atau video telanjangku, kak. Aku takut kak katanya dia akan sebar ke sekolah, akan bilang orang tuaku. Gimana kalau ayah ibuku tahu, kak? Gimana kalo sampe temen-temen atau guruku tahu, kak? Aku harus bagaimana, kak?”. Boleh kamu bayangkan, saat omongan ini aku dengar setiap beberapa minggu sekali, disampaikan oleh anak usia SMP atau SMA, rasanya kepalaku mau pecah.
Sebagai orang yang lebih dulu dewasa, pikiranku penuh dengan kemungkinan-kemungkinan buruk di depan mata, yang siap mencegat kemanapun anak-anak ini melangkah, dan kita sama-sama tahu langkah mereka masih sangat panjang. Saat bicara bentuk-bentuk KBGO yang dialami korban anak, sifatnya berlapis, sekali terjang kena sana-sini. Selain NCII, bisa juga dibarengi dengan Cyberbullying, Sextortion, ataupun Cybergrooming[3]. Semua hal yang bisa dialami korban dewasa, juga mengintai anak-anak yang hadir secara online. Platform yang mentransmisikan juga mirip dengan pola KBGO yang dialami orang dewasa; hubungan-hubungan personal secara offline yang berlanjut ke WhatsApp, atau sebaliknya.
Lalu hal apa yang membedakan? Inginnya sih aku menjawab: “Kebijakan yang ketat melindungi anak-anak dalam online presence nya”, tapi kan tentu saja itu masih di awang-awang. Sayangnya, harus kubilang, karena anak lebih rentan. Mungkin seorang anak bisa sangat fasih main berbagai macam media sosial, tapi sangat mungkin tidak dibarengi dengan pemahaman tentang risiko-risiko yang mengintai. Apakah kemudian ini jadi sepenuhnya salah anak? Tentu tidak! Kita sebagai komunitas juga punya dosa karena tidak mampu (atau tidak mau?) berbagi ruang yang aman untuk anak di ranah online. Bisa jadi, kita sebagai orang dewasa yang berkeliaran di sekitar mereka, menjadi abai dengan batasan-batasan yang mestinya diciptakan untuk melindungi anak. Di media sosial, baik yang viral maupun tidak, pasti ada saja yang melibatkan anak sebagai korbannya. Saat itu terjadi, di mana posisi kita? Coba ingat-ingat lagi gimana respons kita. Marah? Kesal? Mengutuk pelaku sambil menyebarkan berita itu supaya viral dan keadilan ditegakkan? Kalau tidak hati-hati, jangan-jangan kita menjadi pelaku sekunder (bukan pelaku utama yang merekam, tapi jadi pelaku yang ikut menyebarkan konten). Saat niat kita baik, tapi tindakan kita adalah ikut menyebarkan konten atau berita yang mengandung informasi terkait korban anak, disitulah kita ikut melanggar hak-hak anak dan malah membahayakan mereka. Kalau salah satu dari daftar panjang hal-hal yang kamu pedulikan adalah soal anak, maka selalu ingat untuk langsung melapor/report ke platform dan tidak ikut membagikan konten-konten seksual yang melibatkan anak.[4]
Biasanya, saat interaksi dengan anak dalam konteks pendampingan korban, ada harapan yang diutarakan untuk kemudian bisa sama-sama mengatur ekspektasi. Kebanyakan respons anak adalah ingin tetap sekolah. Mereka tahu bahwa dampak yang menghantui adalah kehilangan hak pendidikan. Tentu mereka sadar ini bukan satu-satunya akibat dari KBGO yang dialami. Dalam kebingungan dan ketakutan, anak seringkali masih memaksakan diri menghadapi semuanya seorang diri, karena kalau orang lain sampai tahu, maka ada rasa malu luar biasa, misalnya ketika konten intim mereka ketahuan keluarga, akan dikucilkan teman-teman, dan bisa dikeluarkan dari sekolah. Sudah jadi korban, kehilangan hak, masih juga disalahkan.
Segala luapan emosi dan dampaknya pada hubungan sosial anak, bisa jadi pengalaman yang traumatis dalam masa pertumbuhan mereka. Aku masih mengamini frasa ‘lebih baik mencegah daripada mengobati’. Namun, jika anak sudah menjadi korban KBGO, apa yang bisa kita lakukan? Sebagai bagian dari komunitas ataupun masyarakat, masing-masing kita punya peran. Tujuannya satu, mengembalikan hak-hak anak yang terlanjur hilang. Pertanyaannya, maukah kita jadi support system (sistem pendukung) setiap anak yang ada di sekitar kita? Ruang publik yang kita tempati tidak mungkin terhindar dari kehadiran seorang anak. Hanya karena ruang itu berisiko terjadi kekerasan, bukan berarti anak kita keluarkan dari ruang tersebut. Lebih baik ruangnya lah yang kita upayakan menjadi ruang aman bagi anak, termasuk ranah online. Demi mengarah ke sana, tentu banyak hal yang harus dengan sadar dan sedia kita siapkan.
- Orang dewasa perlu belajar lagi untuk lebih paham keamanan digital bagi diri sendiri dan anak.
- Orang dewasa sudi melibatkan anak dalam pengambilan keputusan, mengakui agensi anak, dan menghormati privasinya.
- Orang dewasa tidak menganggap anak yang menjadi korban sebagai aib, sibuk dengan rasa tidak nyaman, dan tidak mau repot mengusahakan anak agar tetap sekolah.
- Orang dewasa mau membuka diri untuk menjawab pertanyan-pertanyaan anak soal Hak dan Kesehatan Seksual dan Reproduksi (tentu saja ini berhubungan dengan KBGO).
- Orang dewasa benar-benar niat menegakkan hukum untuk perlindungan anak se Indonesia.
Semua subjeknya memang orang dewasa. Aku dan kamu yang membaca. Anak-anaknya sudah siap diskusi soal ruang digital dan KBGO yang siap mencegatnya. Lalu kita, udah siap belum ngobrol terbuka dengan anak?
——
[1] https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak
[2] https://web.tresorit.com/l/0Roy1#mpFeq7gGh9yIqoD37juwpg
[3] https://home.purplecodecollective.net/wp/publikasi/buku-saku/
[4] https://about.meta.com/actions/safety/onlinechildprotection/reporting