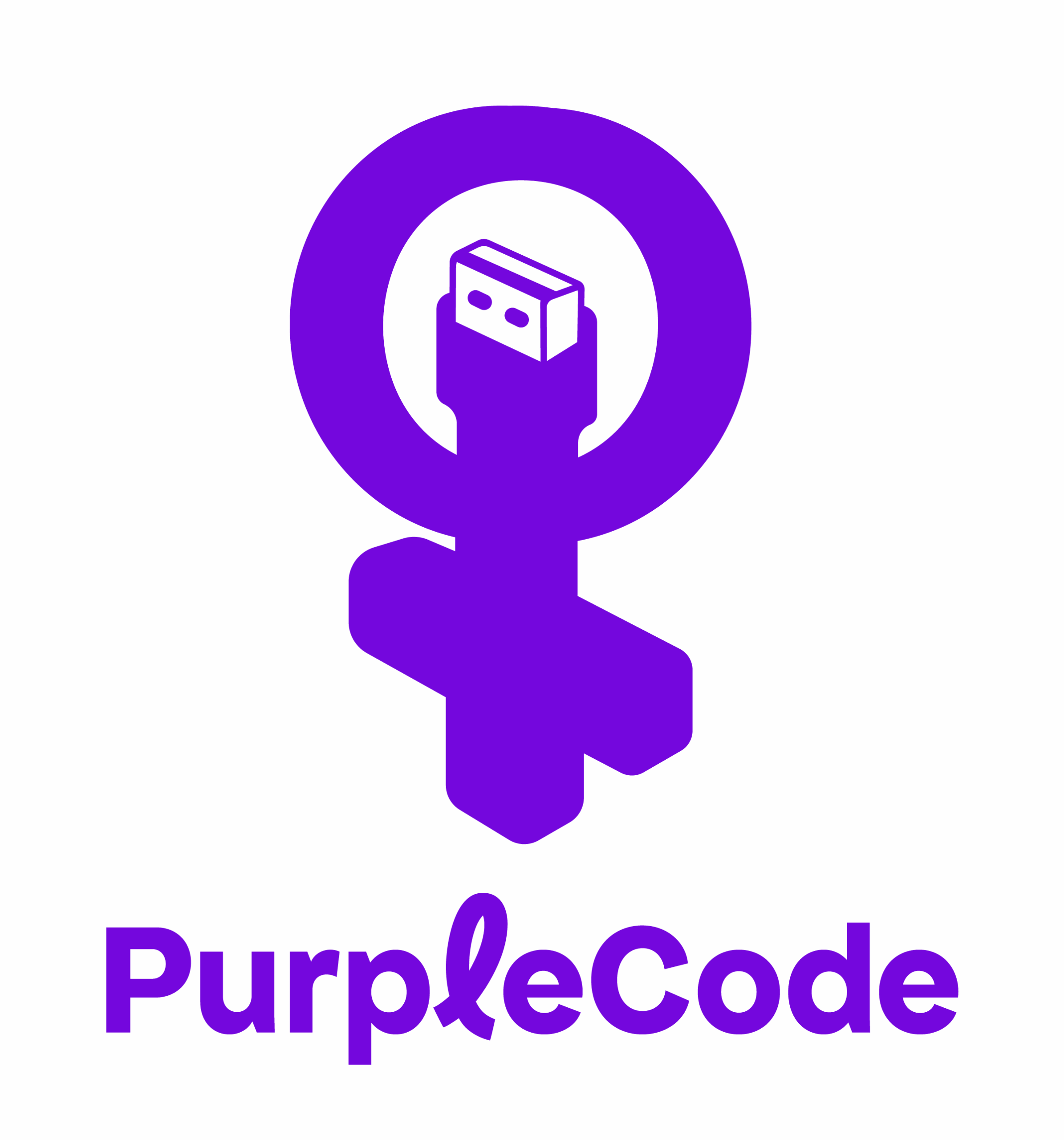13 tahun lalu, saat masih berusia 14 tahun, untuk pertama kalinya aku melihat konten intim. Kejadiannya tak disengaja. Kala itu sedang jam istirahat makan siang. Aku melihat ada sekitar delapan anak laki-laki yang, bahkan hampir setengahnya bukan berasal dari kelasku, tengah riuh bergerombol memadati satu bangku. Aku melihat ada satu orang memegang handphone, sedangkan anak-anak yang lain berusaha merebutnya dari genggaman.
Bingung melihat kelakuan mereka bak bocah PAUD yang berebut mainan, rasa ingin tahuku tergelitik. Aku pun mulai mendekati mereka secara diam-diam dan menyempil masuk di sela-sela kerumunan. Dalam kerumunan itu akhirnya aku tahu apa yang sedang mereka perebutkan.
Mereka sedang berebut nonton konten intim. Entah dari mana mereka mendapatkannya, tapi ketika yang lain sudah mulai “berkelahi”, mereka pun memutuskan menonton bersama tanpa volume. Aku kaget bukan main. Ternyata konten yang tak sengaja aku tonton itu adalah konten yang belakangan jadi buah bibir masyarakat Indonesia. Melibatkan tiga artis ternama Indonesia, satu laki-laki dan dua perempuan.
Tak disangka, kejadian itu jadi awal bagiku melihat fenomena baru di era digital, derasnya persebaran konten intim di media sosial. Bak tsunami yang gulungan ombaknya tak bisa dihentikan, konten-konten ini tersebar bebas lewat pesan berantai WhatsApp hingga Twitter. Mayoritas selalu melibatkan perempuan dan disebarkan secara nonkonsensual.
Aku pun mulai menyadari kecenderungan sikap masyarakat Indonesia. Masyarakat kita hobi sekali menyebarkan konten-konten intim ini dan menjadikannya bahan gossip terkini. Ini terlihat dari kasus salah satu artis Indonesia yang video intimnya disebar di media sosial pada 2020 lalu menjadi bahan perbincangan dia akun-akun gosip. Parahnya, perempuan dan non-conforming gender selalu menjadi sasaran penghakiman. Laki-laki dan pelaku perekam serta penyebar benar-benar dilenyapkan tanpa bekas dalam diskursus yang ada.
Perempuan lagi-lagi harus sendirian menerima konsekuensi atas hal yang bahkan bukan salahnya. Mereka mengalami cyber bullying, doxing, ancaman pemerkosaan atau kematian bahkan dijerat pasal-pasal karet yang menekankan pada moralitas. Beruntung dengan privilese yang aku punya, aku dapat kesempatan belajar tentang Kekerasan Berbasis Gender Online atau KBGO.
Belajar isu KBGO membuatku sadar bisa jadi bagian yang bisa memutus rantai kekerasan di dunia digital yang dialami perempuan. Aku juga bisa jadi bagian dalam memberikan kesadaran dan pencegahan kekerasan bagi orang-orang di sekitarku dan masyarakat luas.
Kombinasi dari tabunya pembahasan soal seksualitas, minimnya akses informasi yang kredibel,serta nihilnya itikad baik pemerintah dalam menyusun kurikulum pendidikan seksualitas yang komprehensif mengakibatkan rendahnya pengetahuan masyarakat pada isu gender, seksualitas, juga Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Ketidaktahuan itu memungkinkan mereka menjadi pelaku sekunder yang ikut menambah lapis kekerasan dan kerentanan korban Bahkan di antara kita juga memungkinkan tidak tau kalau telah menjadi korban atau mengalami kerentanan.
Ketidaktahuan yang timbul karena tiga kombinasi di atas membuat KBGO jadi jenis kekerasan seksual yang semakin marak terjadi. Setidaknya ini tercermin dalam Catatan Komnas Perempuan yang mencatat kenaikan angka KBGO dari 97 kasus pada tahun 2018 menjadi 855 kasus pada 2021. Lebih lanjut, dalam refleksi tahunan TaskForce KBGO baik pada 2021 dan 2022, jenis KBGO yang paling banyak dilaporkan adalah NCII dan sextortion atau pemerasan dengan konten seksual..
Walaupun dengan peningkatan ekstrem kasus-kasus KBGO, masyarakat Indonesia tetap tidak punya akses khusus untuk memahami isu KBGO. ECPAT, INTERPOL, dan Kantor Penelitian UNICEF dalam laporannya pada 2022 misalnya saja mencatat 41 persen dari 955 anak-anak dan remaja Indonesia usia 12 hingga 17 tahun tidak pernah menerima informasi apa pun tentang cara untuk tetap aman saat online.
72 persen anak-anak dan remaja yang yang disurvei mengatakan bahwa mereka tidak menerima pendidikan seksualitas komprehensif yang salah satu didalamnya memuat jenis-jenis kekerasan berbasis gender atau KBG. Lebih dari itu, dari anak-anak yang menerima pendidikan seks, 85 persen mengatakan bahwa pendidikan seks sebagian besar berkaitan dengan moralitas.
Ketabuan dan kurangnya informasi, membuat individu hanya bisa belajar mengenai pendidikan seksualitas komprehensif lewat jalur-jalur tertentu saja. Kalau punya privelese lebih, masyarakat bisa mendapatkannya lewat pendidikan lanjut di perguruan tinggi yang cukup progresif atau dari lokakarya yang dilakukan berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat.
Sisanya? Mereka harus “menemukan” sendiri isu ini dengan keterbatasan yang ada. Dari sulitnya akses pengetahuan KBGO inilah film punya peran penting dalam memberikan pembelajaran dan kesadaran.
Pada 8 Desember 2022, Gina S. Noer merilis film teranyarnya Like & Share. Film Like & Share banyak dapat pujian dari para feminis, kritikus film, hingga penonton awam. Dengan menambatkan fokus pada isu seksualitas dan kekerasan seksual, film Like & Share dengan berani mengeksplorasi isu KBGO yang belum lazim diangkat sineas Indonesia. Dalam durasi 1 jam 52 menit, isu KBGO berusaha dieksplorasi lewat kedua tokohnya, Lisa (Aurora Ribero) dan Sarah (Arawinda Kirana).
Lisa yang sedang mengalami gejolak seksualitas di masa remajanya, gemar melakukan manstrubasi dengan menonton video porno. Kenikmatan eksplorasi seksualitas Lisa harus berbenturan dengan sisi kemausiannya. Ini terjadi ketika ia bertemu korban dari video intim yang ia tonton. Video yang ternyata dibagikan secara nonkonsensual atau dalam istilah KBGO disebut sebagai NCII (Non-Consensual Dissemination of Intimate Images).
Pada saat yang sama, Sarah mulai menjalin hubungan dengan Devan (Jerome Kurnia), laki-laki berusia 10 tahun lebih tua darinya. Dari hubungannya itulah Sarah menjadi korban NCII. Tanpa ada perlindungan khusus yang diakomodasi negara terhadap korban KBGO, Sarah harus mengalami diskriminasi berlapis. Baik teman, guru, bahkan negara tidak berpihak pada Sarah. Undang-undang menghakiminya sebagai pelaku lewat pasal-pasal karet terkait pornografi kendati jelas-jelas ia adalah korban. Sarah pun dibiarkan berjuang sendiri karena telah dicap sebagai pelaku pornografi.
Film Like & Share yang membahas isu KBGO ini tentu membuat penonton berefleksi tentang realita korban. Dialektika seputar hukum yang tak berperspektif korban hingga kekangan budaya patriarki yang berkontribusi dalam menstigma dan melanggengkan kekerasan jadi riuh dibincangkan. Kesadaran pun jadi terbangun selama prosesnya. Dalam perbincagan yang aku ikuti di Twitter, beberapa kali aku melihat ada beberapa warganet yang akhirnya menyadari sekolah dan instrumen hukum Indonesia tidak berpihak pada korban KBGO.
Pendidikan seksualitas komprehensif pun sangat minim bahkan tak ada sama sekali di sini, sehingga murid-murid terutama perempuan tak awas dengan kerentanan mereka dalam mengalami KGBO.
Mengutip penelitian Nokukhanya Ngcobo, pengajar di Sekolah Pendidikan di Afrika Selatan yang terbit pada 2015, film sebagai medium memang mampu menghadirkan realita baru dengan cara meleburkan batas antara ‘kita’ dan ‘mereka’. Film didesain untuk menumbuhkan perasaan pada penonton lewat protagonis dan karakter-karakternya. Salah satu perasaan itu adalah empati, tulis Nokukhanya Ngcobo dalam penelitiannya yang sama berjudul The use of film as an intervention in addressing gender Violence: Experiences in a South African secondary school.
Dengan menggunakan isu dan teks-teks tertentu, film berperan penting memberikan kesempatan bagi para penonton untuk terlibat secara emosional dengan karakter-karakter yang ada. Ini adalah pintu masuk yang ideal secara pedagogis bagi penonton untuk mendiskusikan dan membicarakan isu-isu sosial dan interseksinya seperti gender, ras, kemiskinan, kekerasan gender, seksualitas, dan sebagainya.
Melalui film yang meleburkan batasan ‘kita’ dan ‘mereka’, penonton jadi mampu mengenali dan menantang perspektif bias yang tertanam dalam teks. Ini dapat memberikan efek positif terhadap penonton untuk terlibat aktif dalam menentang keyakinan dominan di dalam masyarakat yang terinternalisasi kuat terkait ketidaksetaraan gender dan kekerasan gender.
Kekuatan film salah satunya dimanfaatkan oleh United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). Dalam laman resminya, UNHCR membantu menyebarkan kesadaran tentang kekerasan seksual di Republik Demokratik Kongo melalui pemutaran film di bioskop keliling yang berjudul “Breaking the Silence”.
Dalam satu testimoni, seorang perempuan mengatakan penayangan film ini menggugah orang-orang untuk lebih memahami kondisi korban, menyerukan kepada para pelaku untuk mengakhiri praktik-praktik kekerasan dan mendesak pihak berwenang untuk menerapkan hukum berperspektif korban.
Tidak mengherankan kemudian Lena Slachmuijlder, kepala Search of Common Grounds di Kongo mengatakan film adalah alat yang sangat kuat dan tepat untuk mengatasi tabu, stereotip seputar kekerasan berbasis gender. Nantinya, film akan berperan penting dalam mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam mendorong kesetaraan dalam kebijakan dan produk hukum di berbagai sektor. Hal ini tak lain karena film punya peran penting dalam membangun kesadaran dan perubahan perilaku kelompok masyarakat.