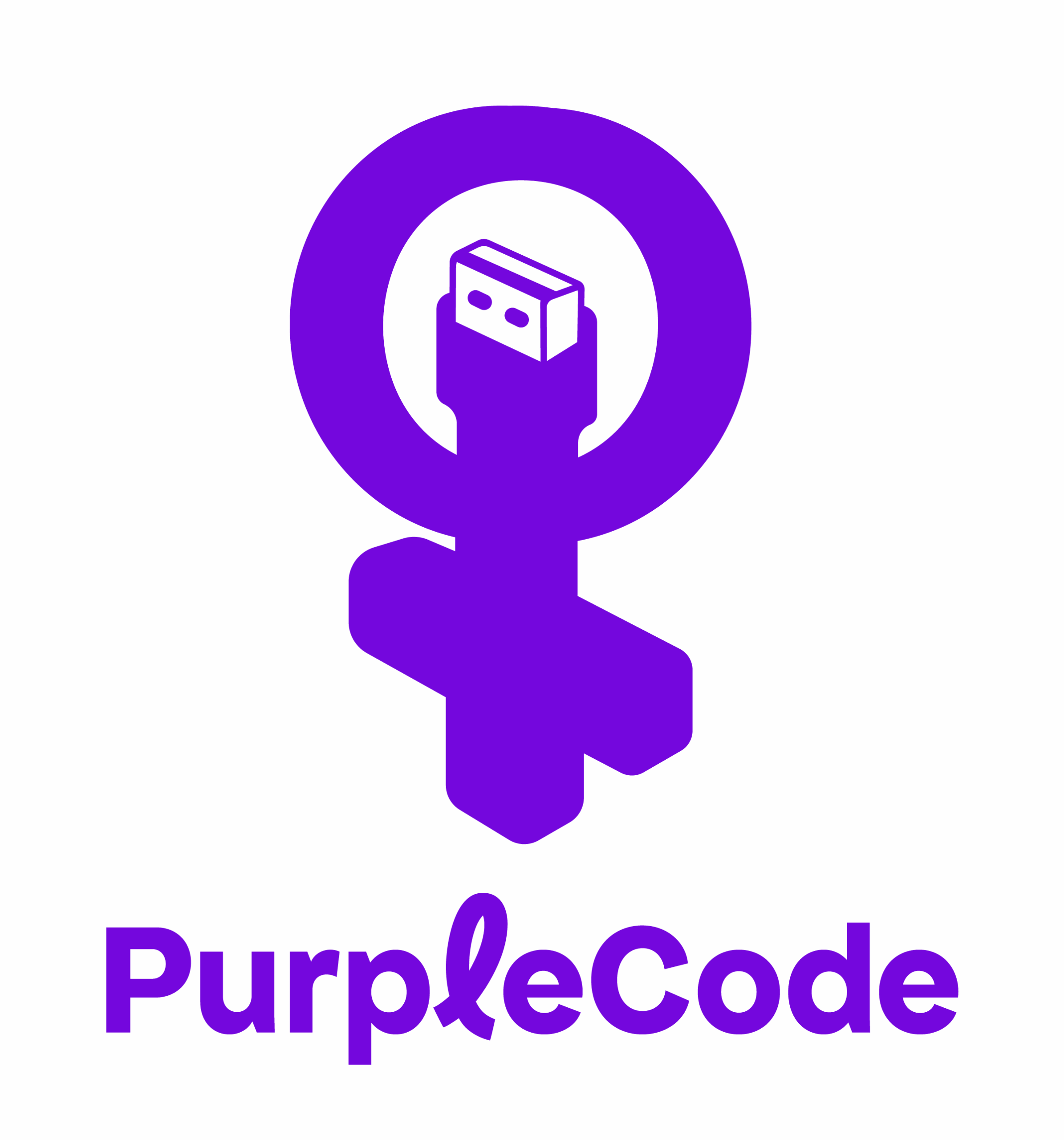Selamat malam, salam sehat rekan-rekan sekalian.
Sebelum memulai pemaparan saya, saya ingin desclaimer terlebih dahulu bahwa dalam kurang lebih 15 menit kedepan saya tidak akan bicara soal konsep dekolonisasi, saya minta maaf karena saya tidak memiliki keahlian di sana.
Selanjutnya, saya ingin mengucapkan selamat kepada Purple Code atas kegiatan Dekode Fest yang saya lihat di ToR sangat luar biasa dan membawa kebaruan dalam membumikan percakapan feminis dan teknologi di Indonesia.
Kawan-kawan sekalian, saya ingin memulai dari pengenalan latar belakang saya. Saya menempuh studi pendidikan teknologi selama 7 tahun, 3 tahun di SMK dengan jurusan teknik komputer jaringan, dan 4 tahun di kuliah s2 jurusan teknik informatika. Selama 7 tahun tersebut saya belajar dan bekerja paruh waktu di isu teknologi seputar membuat website, memperbaiki komputer dan seterusnya bahkan sejak saya masih bersekolah di SMK.
Fast forward setelah 7 tahun menggeluti studi teknologi, saya beralih ke studi gender tanpa sengaja. Saya menyadari bahwa sejak SMP saya sangat menyukai menulis dan karya sastra, waktu itu ayah saya mendorong saya untuk studi di SMK dengan asumsi bisa langsung bekerja dan membantu perekonomian keluarga. Sebagai anak saya tidak punya pilihan terlalu banyak pada saat. Setelah lulus kuliah, saya secara tidak sengaja bertemu Jurnal Perempuan, saya membaca apa itu feminisme dari Jurnal Perempuan, saya jatuh cinta. Semesta menyambut saya kemudian menjadi terlibat dalam kerja-kerja Jurnal perempuan di tahun 2015 hingga membantu mengembangkan open journal system. Dari sana saya diberikan kesempatan oleh ibu gadis arivia dan mbak dewi candraningrum untuk melanjutkan studi di program studi kajian gender, tentu saya menerima dengan senang hati. Saya kemudian mendalami studi gender, menulis, meneliti, dan secara keras kepala memiliki isu feminisme dan teknologi sebagai tesis saya.
Itu sedikit latar belakang saya yang ingin saya sampaikan di awal. Karena ketika bicara feminisme kita selalu berangkat dari pengalaman yang yang personal. Kawan-kawan sekalian, baru saja BBC merilis berita bahwa Ilmuwan Indonesia, Carina Joe, di balik tim Oxford AstraZeneca, vaksin yang terbanyak disebar di dunia, akan wakili tim terima penghargaan Pride of Britain. Kawan-kawan, melihat berita ini seakan-akan mata kita terbuka bahwa perempuan memiliki peran dalam perkembangan ilmu pengetahuan, sains dan teknologi.
Marie Curie, Hypatia, Rosalind Franklin, Patricia Bath, Katherine Johnson, Dorothy Vaughan, dan Mary Jackson adalah sebagian dari perempuan-perempuan yang tercatat berkiprah dalam bidang sains dan teknologi. Eksistensi perempuan di bidang sains dan teknologi kerap luput atau jarang terdengar dalam catatan dunia ilmu pengetahuan, tak heran jika lebih banyak nama-nama ilmuwan laki-laki yang dimunculkan di dalam sejarah ilmu pengetahuan, seperti Isaac Newton, Albert Einstein, dan lainnya.
Filsafat Feminis dan teknologi
Filsafat feminis sains dan teknologi muncul di tahun 1970-an sebagai bagian dari gelombang kedua aliran feminisme. Para pemikirnya antara lain Evelyn Fox Keller, Donna Haraway dan Sandra Harding Para feminis tersebut mendekati dan menggugat teori-teori maupun ilmu pengetahuan yang selama ini memiliki standar positivistik, objektivistik, dan teknokratik (Dusek, 2006: 137).
Para feminis sains dan teknologi memetakan tiga area yang perlu diinvestigasi dari hubungan perempuan dan teknologi yaitu menyoal kontribusi perempuan dalam penemuan teknologi, pengaruh teknologi rumah tangga dan reproduksi terhadap perempuan dan metafora atas teknologi vs alam sebagai maskulinitas vs feminitas.
Pertama, kontribusi perempuan dalam teknologi dan penemuan dipertanyakan oleh para feminis. Di tahun 1960-an, dalam ilmu antropologi muncul teori tentang homosapiens modern yang disebut “Man The Hunter”. Teori tersebut beranjak dari klaim peradaban bahwa berburu dianggap sebagai pusat perkembangan manusia dan kerjasama sosial, laki-laki lebih dominan dalam berburu sehingga dianggap lebih bertanggung jawab pada kemajuan sosial dan umat manusia. Teori tersebut dikritik oleh Ruth Hubbard dengan melontarkan pertanyaan, “Apakah hanya manusia laki-laki yang berevolusi?”. Di tahun 1970-an para antropolog perempuan dengan pengaruh pemikiran feminisme memunculkan teori “Women Gatherer”, yang artinya perempuan telah berkontribusi terhadap persediaan makanan umat manusia dengan mengumpulkan tanaman, kacang-kacangan dan biji-bijian. Para antropolog tersebut mengklaim bahwa menyediakan makanan dari tumbuh-tumbuhan lebih penting daripada melakukan perburuan besar-besaran (Dusek, 2006).
Perdebatan tentang siapa, laki-laki atau perempuan yang menjadi pusat kemajuan teknologi tidak berhenti sampai di situ, Lewis Mumford juga mengkritik para sejarawan teknologi yang kerap kali melupakan kontribusi perempuan dalam sejarah kemajuan teknologi, ia mengungkapkan bahwa jika alat transportasi adalah kepanjangan dari kaki, maka rahim dan payudara tak bisa dilupakan sebagai perpanjangan teknologi penyimpanan dan inkubasi itu sendiri.
Salah satunya ialah Voltaire, yang menyatakan bahwa perempuan bukanlah penemu/ilmuwan, jika memang ada maka keberadaannya perlu ditutupi, dan perempuan hanya membuat penemuan yang mereka sukai saja atau disebut “pekerjaan perempuan”. Ann Harned misalnya, ia menemukan penuai mekanik bersama suaminya namun hanya suaminya yang diumumkan sebagai penemu teknologi tersebut. Sayangnya, argumen Voltaire sepertinya lebih didengar oleh peradaban patriarki sehingga para penemu dan ilmuwan perempuan seakan-akan tak memiliki kontribusi apapun dalam kemajuan dan inovasi teknologi. (Dusek, 20016: 139).
Kedua, teknologi memiliki dampak spesifik bagi perempuan. Val Dusek dalam Philosophy of Technology (2006) menjelaskan bahwa setidaknya ada dua jenis teknologi yang memiliki dampak langsung dan mempengaruhi peran-peran perempuan dalam struktur sosial, yaitu teknologi rumah tangga dan teknologi reproduksi. Mesin cuci, oven, vacum cleaner, microwave dan kompor gas adalah beberapa diantara produk teknologi rumah tangga. Bagi perempuan kelas atas, kehadiran teknologi rumah tangga dianggap telah berkontribusi terhadap kerja-kerja rumah tangga mereka dengan membuat pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat. Namun bagi perempuan miskin, kehadiran teknologi rumah tangga yang memberikan efisiensi waktu tersebut tak cukup karena pada faktanya tak ada pengurangan beban kerja rumah tangga mereka, semakin banyak pakaian yang harus dicuci, semakin luas rumah yang harus dibersihkan.
Oven membuat aktivitas fisik untuk memasak berkurang, begitu juga dengan keahlian memasak semakin hilang. Hal ini juga berdampak pada penghormatan suami terhadap kerja-kerja istri. Hadirnya teknologi rumah tangga membuat istri dianggap ‘tidak bekerja’ oleh suami mereka. Lebih jauh, Dusek juga mengemukakan bahwa teknologi rumah tangga membuat perempuan jadi konsumen atau pengguna dan laki-laki menjadi pembeli, desainer, petuga servis dan lai-lain.
Sulamith Firestone dalam Dialectic of Sex (1970) menyatakan bahwa memisahkan perempuan dari rahim biologisnya adalah cara untuk mencapai kesetaraan yang seutuhnya. Ini adalah awal mula dimana teknologi reproduksi dianggap sebagai penyelamat perempuan (Dusek, 2006). Gagasan Firestone mendapatkan kritik dari berbagai feminis karena tak sepenuhnya teknologi itu netral gender.
Pada faktanya teknologi reproduksi dikuasai oleh laki-laki, dokter laki-laki memiliki kontrol penuh atas tubuh perempuan, meskipun di satu sisi ada teknologi kontrasepsi dan aborsi memungkinkan perempuan mendapatkan kontrol atas tubuhnya dengan penuh dan teknologi fertilasi dan implantasi embrio menjadi sebuah pengharapan bagi perempuan. Teknologi ultrasound, operasi caesar, seleksi gender janin adalah contoh teknologi reproduksi yang dicurigai dan berpotensi menghilangkan kemampuan subjek kehamilan itu sendiri yaitu perempuan. Diskursus mengenai teknologi reproduksi terus terjadi, perempuan diharapkan dapat memanfaatkan teknologi reproduksi namun perlu waspada karena ada ideologi patriarki di dalamnya. Bahkan Dusek mengungkapkan bahwa teknologi reproduksi adalah saran dokter laki-laki untuk mengendalikan kehamilan dan persalinan yang tidak bisa ia lakukan.
Ketiga, metafora teknologi sebagai laki-laki dan alam sebagai perempuan. Metafora tersebut pada akhirnya mengandaikan bahwa laki-laki bersifat aktif dan perempuan adalah pasif. Namun menurut Dusek, metafora tersebut juga tak sepenuhnya diamini dalam sains dan teknologi, banyak anggapan bahwa metafora hanyalah hiasan luar yang tak penting karena eksperimen, hukum alam, penemuan mekanis berdiri sendiri tanpa identitas gender tertentu. Namun metafora tersebut tidak dapat diabaikan karena berpengaruh terhadap perekrutan dan motivasi perempuan untuk menjadi ilmuwan dan insinyur. Evelyn Fox Keller menganalisis berangkat dari teori Chodorrow yang menyatakan bahwa anak laki-laki harus memutuskan hubungan dengan ibu mereka dalam rangka pembentukan identitas sedangkan hal tersebut tidak terjadi pada perempuan. Hal tersebut berkaitan dengan stereotip maskulin pada sains dan teknologi yang mengunggulkan objektivitas dan tidak bergantung seperti halnya laki-laki. Tentu citra maskulin sains dan teknologi berdampak pada perekrutan perempuan. Anak perempuan di sekolah menengah atas yang memiliki bakat sains dan teknologi akhirnya tidak dianjurkan untuk mengejar studi lanjutan untuk menjadi ilmuwan sains maupun seorang insiyur (Dusek, 2006).
Gambaran sains dan teknologi yang dibangun bertentangan dengan gambaran dan ekspektasi masyarakat terhadap femininitas anak perempuan sehingga banyak anak perempuan yang merasa takut untuk menjadi cerdas atau merasa kemampuan tekniknya lebih baik dari laki-laki karena khawatir laki-laki tidak tertarik padanya (Dusek, 2006).
Tiga aspek di ini merupakan wacana perempuan dan teknologi yang memungkinkan saling bertentangan satu sama lain. Diskursus di atas memberikan gambaran besar tentang relasi perempuan dan teknologi yang terjadi di berbagai dimensi, baik itu level privat maupun publik. Sayangnya keduanya tak bisa dipandang hitam dan putih dan dikotomis, persoalan teknologi yang seakan-akan berada di level publik ternyata masuk dan menyergap diam-diam pada urusan privat perempuan yaitu tubuh. Teknologi sendiri dipahami Dusek bukan hanya perangkat keras atau penemuan ilmiah-objektif namun juga sebagai sebuah sistem sosial. Teknologi sebagai sebuah tidak melibatkan metafora atau ideologi gender namun teknologi sebagai sebuah sistem sosial dan budaya melibatkan citra dan metafora sehingga pengguna memiliki peran-peran dalam teknologi.
Cyborg
Donna Haraway dalam bukunya Cyborg Manifesto menggugat dominasi maskulin dalam ilmu pengetahuan sains dan teknologi. Hawaray menciptakan sebuah metafora yaitu Cyborg, sebuah strategi retorik dan alat politik yang manjur untuk melakukan perlawanan, atas aturan-aturan yang tidak adil, bias dan misoginis. Keimanan yang ironis, Cyborg adalah manusia dengan fungsi mesin di kaki dan tangannya, tetapi dia tetap mengandung daging di dalamnya, semacam makhluk hybrid (Haraway, 1984: 291).
Dalam salah satu bab yang berjudul “A Cyborg Manifesto: Science, Technology, and Socialist-Feminism in the Late Twentieth Century” (1984), Haraway menjelaskan bagaimana perempuan selama ini diletakkan dalam posisi gender biner yang sebenarnya memenjara eksistensinya sendiri. Melalui metafora Cyborg, Haraway hendak menjelaskan bahwa perempuan memiliki entitas yang cair dan bersilang, antara mesin dan daging. Bagi Haraway cyborg adalah alat perlawanan politik untuk mendekonstruksi hierarki dan hegemoni dalam dunia yang bias. Cyborg merupakan perlawanan Haraway terhadap semua konsep yang dibangun, baik oleh feminis maupun bukan, atas naturalisme dan esensialisme.
Bagi Haraway, sains yang selama ini tak terbantahkan keabsahannya, justru merupakan lokus dimana seluruh bias dalam epistemologi ilmu pengetahuan modern dibangun. Menurutnya Sains dan Teknologi perlu didekonstruksi, dibongkar dan diperdebatkan kekuasaanya. Maka perempuan perlu menguasai sains dan teknologi, kalau tidak, akan tertindas dan dieksploitasi secara menerus sampai menggerus. Perempuan harus mampu merebut kembali sains sebagai alat kemerdekaan, sebagai alat penyumbang keadilan. Baginya, meskipun Cyborg setengah mesin, dia adalah makhluk organik yang menikmati diri dalam sebuah mesin.
Persoalan dualisme pun digugat oleh Sandra Harding dalam bukunya The Science Question in Feminism (1986). Dalam ilmu perkembangannya ada dualisme, budaya vs alam, pikiran rasional vs tubuh yang tak rasional, objektivitas vs subjektivitas, publik vs privat, kemudian laki-laki diasosiasikan sebagai yang rasional, berada di ruang publik sedangkan perempuan sebaliknya. Para feminis kemudian mengkritik dan menjelaskan bahwa ternyata dikotomi tersebut telah berubah menjadi sebuah ideologi yang sangat kuat, yang kemudian berada dalam struktur politik, institusi sosial, termasuk ilmu pengetahuan dan sains (Harding, 1986: 136)
Technofeminism
Menurut Wacjman kecakapan dalam bidang teknis masih masih menjadi hegemoni maskulinitas dalam masyarakat barat. Perlakukan di masa kanak-kanak yang berbeda untuk teknologi, prevalensi peran yang berbeda, bentuk sekolah yang berbeda, dan pembagian kerja berdasarkan seks dalam pasar, menggambarkan “konstruksi manusia laki-laki sebagai yang kuat, mampu di bidang teknologi sedangkan perempuan secara fisik dan teknis tidak mampu dalam bidang teknologi”. Untuk memasuki domain teknis tersebut (baca: teknologi) perempuan perlu mengorbankan aspek utama dari femininitas mereka.
Teori Technofeminism Judy Wacjman dalam Feminisme versus Teknologi (2001) menguraikan bahwa kurangnya keberadaan perempuan dalam dunia teknik sering dialihkan seolah-olah masalahnya adalah kurangannya rasa percaya diri pada perempuan. Tetapi dominasi laki-laki dalam sebagian besar teknologi telah diamankan dengan pengucilan perempuan dari area-area teknologi. Menurut Judy Wacjman perempuan memiliki kemampuan intelektual yang sama dengan laki-laki. Namun kita bisa melihat bahwa sebenarnya hambatan itu diciptakan sendiri oleh lingkungan, dimana perusahaan melebih-lebihkan apa yang disebut “keterbatasan perempuan”. Ideologi patriarkal melebih-lebihkan perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, memastikan bahwa laki-laki akan selalu dominan dan perempuan akan selalu mendapatkan peranan yang lebih rendah. Ideologi ini sangat berkuasa sehingga sekilas terlihat perempuan menerima penindasan yang dialaminya.
Lebih jauh, Wacjman mengungkapkan bahwa teknologi memiliki dimensi politis. Sama halnya dengan sains, teknologi dianggap sebagai sumber pengetahuan ilmiah-rasional, dan menolak hal-hal yang bersifat intuitif-emosional. Dikotomi antara yang rasional dan intuitif ini ditimpakan kepada perempuan yang kerap dikontruksi sebagai yang makhluk yang tidak rasional. Perempuan pun dijauhkan dari sains dan teknologi, karena dianggap tidak mampu menyelesaikan perhitungan dan konsepkonsep besar sains dan teknologi. Para feminis telah lama memperdebatkan tuduhan terhadap ketidakmampuan perempuan dalam bidang sains dan teknologi tersebut.
Pendekatan technofeminism yang diajukan Judy Wacjman memungkinkan kita melihat teknologi dengan cara pandang baru, bahwa teknologi adalah cair and fleksibel. Dengan begitu kita dapat mendefinisikan ulang kehadiran teknologi yang awalnya “technophobia” menjadi “technophilia”.
Technofeminism memperlihatkan praktik, desain dan inovasi teknologi tidak menuntut pengguna tertentu, sehingga penjaminan atas sistem informasi yang inklusif perlu dilakukan dan sangat penting untuk melibatkan perempuan dalam seluruh proses inovasi teknologi. Dengan demikian, technofeminism melihat bahwa maskulinitas dan femininitas adalah karakter yang dilekatkan pada teknologi, pada mulanya teknologi tidaklah bergender sehingga memungkinkan untuk didefinisikan ulang.
Melalui tulisan ini Wacjman hendak memberikan gambaran technophobia (rasa takut terhadap teknologi, pesimisme) dan technophilia (perayaan terhadap kehadiran teknologi, oprimisme) dengan mengajukan apa yang disebut dengan pendekatan techofeminism—kombinasi antara kajian feminisme dengan teknologi. Pendekatan technofeminism menekankan bahwa relasi gender dan teknologi adalah cair dan fleksibel dan persoalannya bukanlah pada teknologi tapi pada politik feminis. Dengan demikian, technofeminism melihat bahwa maskulinitas dan femininitas adalah karakter yang dilekatkan pada teknologi, pada mulanya teknologi tidaklah bergender sehingga memungkinkan untuk didefinisikan ulang.
Feminisme Digital: Kuasa dan Eksklusi
Feminisme di ruang digital tidak bisa dilepaskan dari sejarah panjang kajian feminisme dan teknologi. Dalam kajian feminisme dan teknologi, kemutakhiran teknologi tidak dilihat sebagai sebuah hal yang netral, sebab teknologi berperan dalam relasi kekuasaan berbasis gender. Dalam konsep teknologi tradisional, kemajuan teknologi masih seputar tentang mesin industri, senjata militer, alat perang, dan teknologi lain yang mempengaruhi sebagian besar aspek kehidupan manusia sehari-hari. Sebaliknya, teknologi bagi perempuan adalah teknologi domestik misalnya teknologi mesin cuci, penanak nasi, pembersih ruangan (Wajcman 1991). Tantangan untuk para feminis mulai menunjukkan bahwa identifikasi terhadap teknologi yang dilekatkan pada maskulinitas dan jenis kelamin perlu direkonstruksi (Wacjman 2009).
Internet di akhir 60-an dan jejaring www (world wide web) memberikan angin segar bagi feminis untuk mendekatkan diri pada berbagai jenis teknologi baru (Candraningrum 2013). Kajian mengenai feminisme dan teknologi kemudian bertumbuh melampaui konsep teknologi tradisional. Pada era ini muncul kajian cyberfeminism yang lebih optimis menyambut internet dan hubungannya dengan identitas (Haraway 1985; 1997). Internet dianggap telah menyediakan dasar teknologi untuk membentuk masyarakat baru dan keragaman subjektivitas yang inovatif. Teknologi baru ini juga memfasilitasi kaburnya batas-batas antara manusia dan mesin serta batas-batas laki-laki dan perempuan, yang memungkinkan pengguna untuk memilih identitas mereka, menyamar, dan menganggapnya sebagai identitas alternatif (Haraway 1985, Wajcman 2006).
Lebih jauh, kehadiran internet juga memberikan ruang bagi publik untuk melakukan aktivisme feminis (Fotopoulou 2016). Salah satu contohnya adalah kelahiran petisi online sebagai upaya untuk menginisiasi keadilan bagi kelompok marginal di akhir 90an. Ruang digital telah mengubah wajah aktivisme feminis yang sebelumnya turun ke jalan menjadi panggung dimana orang-orang bisa membentangkan spanduk protes dan kampanye melawan ketidakadilan, kesewenangan, dan otoritarianisme (Candraningrum 2013).
Aktivisme offline tradisional memobilisasi orang melalui kampanye jalanan atau dari pintu ke pintu, dengan bantuan jaringan sosial yang ada dan keanggotaan organisasi, partai politik, atau lembaga pendidikan. Sedangkan, aktivisme digital, dapat memobilisasi sejumlah besar orang dalam hitungan menit, jauh lebih cepat daripada aktivisme offline. Model aktivisme ini juga mendorong pendekatan yang interaktif, di mana beragam kelompok orang dapat berpartisipasi melalui blog online, petisi, dan artikel sambil terhubung dengan orang lain. Sebelum adanya ruang digital, gerakan feminis global sebagian besar dibentuk oleh segelintir orang melalui wacana akademisi feminis (Jain 2020).
Teknologi baru seperti media sosial, petisi online, maupun aplikasi donasi pada praktiknya tidak berlaku sama pada semua orang. Bagi sebagian kelompok, teknologi dan media baru adalah ruang strategis untuk aktivisme, ruang yang menyediakan kesempatan, dan peluang untuk terhubung dengan kehidupan masyarakat secara langsung. Bagi sebagian kelompok yang lain, media digital adalah ruang yang bergender (gendered space) yang mengakomodir hanya identitas-identitas tertentu dan memarginalkan identitas lain seperti perempuan lanjut usia atau bahkan transgender (Fotopoulou 2016).
Sama halnya dengan ruang luring, ruang digital (daring) tidak terlepas dari bias-bias maskulinitas dan patriarki dimana perempuan dan kelompok marginal harus terus waspada kepada diskriminasi gender dalam struktur sosial baru. Secara kritis, para feminis tidak pernah berhenti untuk terus mempertanyakan opresi terhadap perempuan dan kelompok marginal sebagai sebuah jalan menuju objektivitas yang feminis (standpoint feminist) (Harding, 1986). Berangkat dari cara berpikir standpoint feminist, anggapan mengenai teknologi sebagai ruang alternatif yang menyuarakan suara kelompok marginal, bebas intervensi, dan memungkinkan bentuk-bentuk aktivisme baru non-konvensional perlu diselidiki lebih jauh.
Ada tiga faktor yang paling mempengaruhi partisipasi seseorang, organisasi, maupun gerakan feminis dalam aktivisme digital yakni usia, kurangnya sumber daya, dan literasi media. Ketiga faktor tersebut bisa menjadi pendorong kelompok tertentu untuk mendapatkan publikasi dan pengakuan dalam aktivisme digital dan secara bersamaan dapat menjadi ruang eksklusi. Berbeda dengan artis atau publik figur, para aktivis yang memanfaatkan ruang digital kerap kali tidak bisa mendapatkan pengakuan karena keterbatasan sumber daya, termasuk keterampilan di medium digital. Hal ini tentu akan berbeda, pada aktivis maupun organisasi perempuan yang fasih menggunakan medium digital (digital native)—yang didominasi oleh aktivis muda perkotaan yang tumbuh bersama kemajuan media baru (Fotopoulou 2016; Lim 2015).
Argumen bahwa ruang digital menjadi ruang baru untuk perempuan mendapatkan kebebasan telah disinggung oleh Sulamith Firestone seorang pemikir feminis gelombang kedua. Feminisme radikal Firestone berpendapat untuk masa depan di mana teknologi digunakan untuk menghilangkan seksisme dengan membebaskan wanita dari persalinan dan membebaskan pria dan wanita dari keluarga inti patriarki. Dalam banyak hal penting, karya Firestone adalah cikal bakal penulisan cyberfeminist kontemporer, terutama karya Donna Haraway (Halbert 2007). Kehadiran ruang digital dianggap menjanjikan bagi perempuan. Bagi para aktivis feminis siber, media digital sebagai ruang elektronik baru menawarkan awal yang baru bagi perempuan untuk menciptakan bahasa, program, platform, gambar, identitas yang cair, dan multi-bahasa baru. Perempuan dan kelompok marginal di dunia maya berperan sebagai subjek yang bisa mengkode ulang, mendesain ulang, dan memprogram ulang teknologi informasi untuk membantu mengubah kondisi sosial menjadi lebih adil, inklusif, dan feminis (Jain 2020).
Meski menyediakan kesempatan baru, namun ruang dan teknologi digital sendiri tidak serta merta ruang yang aman dan inklusif. Penting untuk menyadari bahwa kehadiran media baru tidak bisa dilepaskan dari struktur sosial, ekonomi, politik, budaya yang sudah mapan–yang mana sangat seksis dan rasis. Kehadiran ruang digital dan pertukaran informasi lintas batas, tidak tidak secara otomatis melenyapkan hierarki dan patriarki. Ruang digital dan internet secara sosial berkaitan dengan tubuh, jenis kelamin, usia, ekonomi, kelas sosial, dan ras. Mengupayakan keadilan dan aksi feminis di dunia maya sama hal dengan mengganggu kode-kode maskulin dan tatanan patriarki yang secara inheren telah ada bersamaan dengan kehadiran teknologi baru (Wilding 2006).
Lebih lanjut menyoal peluang dan tantangan dalam aktivisme digital, Fotopoulou (2016) dalam bukunya Feminist Activism and Digital Networks Between Empowerment and Vulnerability menjelaskan dua konsep utama sebagai pisau analisa melihat aktivisme digital feminis. Pertama feminisme jaringan (networked feminism) menggambarkan identitas kolektif dan praktik komunikatif para aktivis karena mereka dibentuk oleh imajinasi ruang sosial baru (dipahami sebagai jaringan) dan keterhubungan digital. Kedua, konsep kerentanan biodigital (Biodigital Vulnerability) yang mampu mengurai kompleksitas produksi konten dan kuasa yang membentuk jaringan online sebagai ruang yang saling bertentangan, antara pemberdayaan dan kerentanan bagi politik feminis. Fotopoulou (2016) menjelaskan bahwa ada kerentanan yang muncul ketika publik melihat ada potensi politik di ruang digital untuk memberdayakan masyarakat dan individu yang terpinggirkan atau menjadi korban karena seksualitas dan gender mereka.
Haraway (1997) kemudian menyebut bahwa kerentanan di ruang digital ini sebagai akibat dari ‘technobiopower’—melanjutkan apa yang ditulis Foucault (1978) sebagai biopower. Artinya ada jenis kerentanan baru yang dihasilkan dari aktivisme di dunia digital. Ketika individu aktif di ruang digital dan menggunakan teknologi baru, mereka tidak hanya terlacak melalui kata-kata yang diunggah di laman sosial media saja, tetapi dalam seluruh aplikasi dan data yang mereka ikuti. Jejak digital, identitas, privasi menjadi amat transparan. Bagi kelompok perempuan, anak, dan kelompok minoritas, ruang digital memungkinkan mereka mengalami kekerasan seksual, terlibat dalam sexting, hingga mengalami perundungan siber (cyberbullying). Meski memungkinkan hadir sebagai anonim, tetapi dampak dari bullying dan kekerasan yang terjadi oleh tubuh-tubuh individu ini dialami secara nyata–misalnya kasus bunuh diri karena fitnah, stigma sosial, dan perundungan (bully) di media sosial (Fotopoulou 2016).
Merayakan sekaligus menyadari kerentanan bahwa patriarki Ruang digital menjadi belenggu bagi agenda-agenda politik feminis.
Ditulis oleh Andi Misbahul Pratiwi