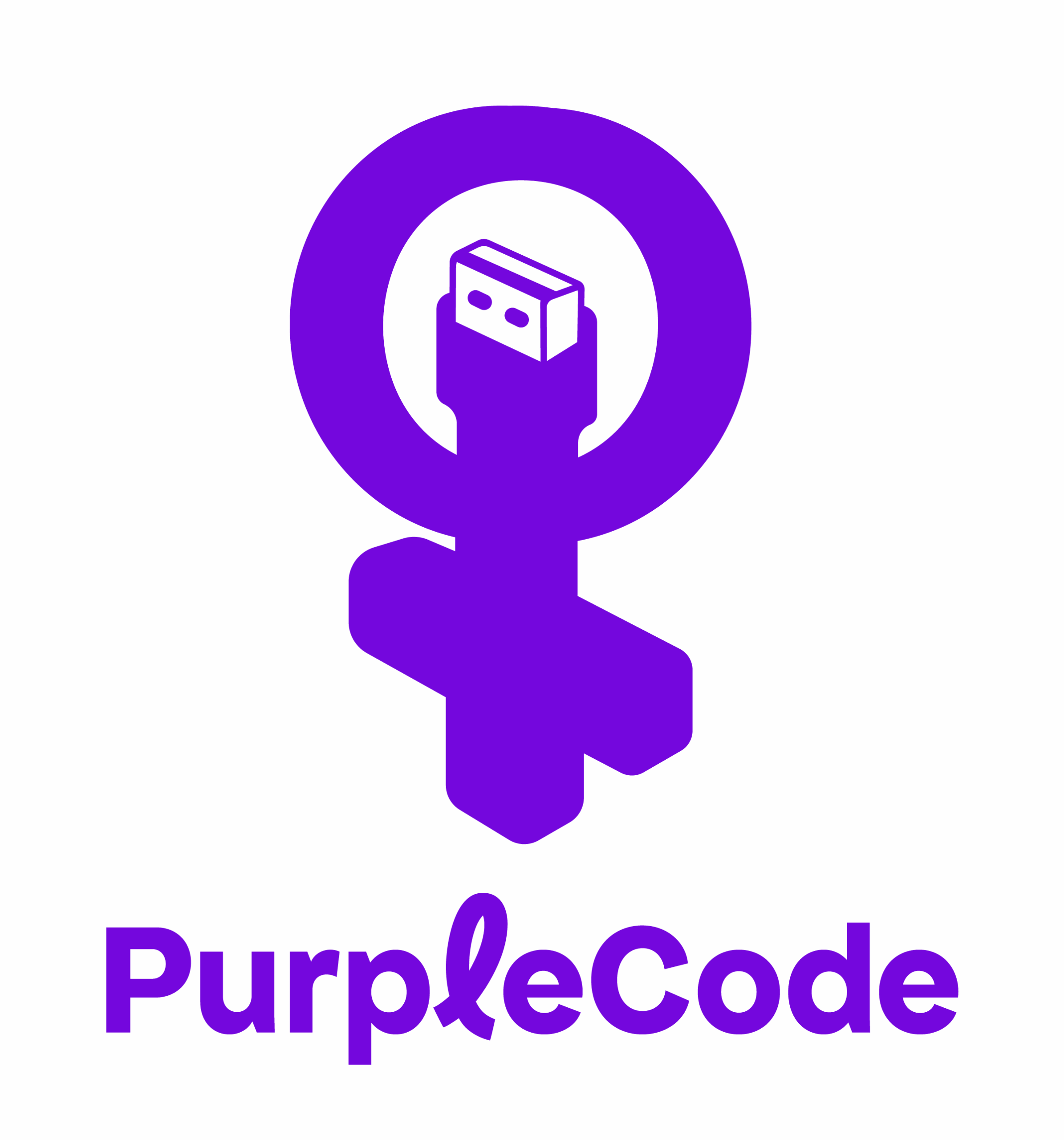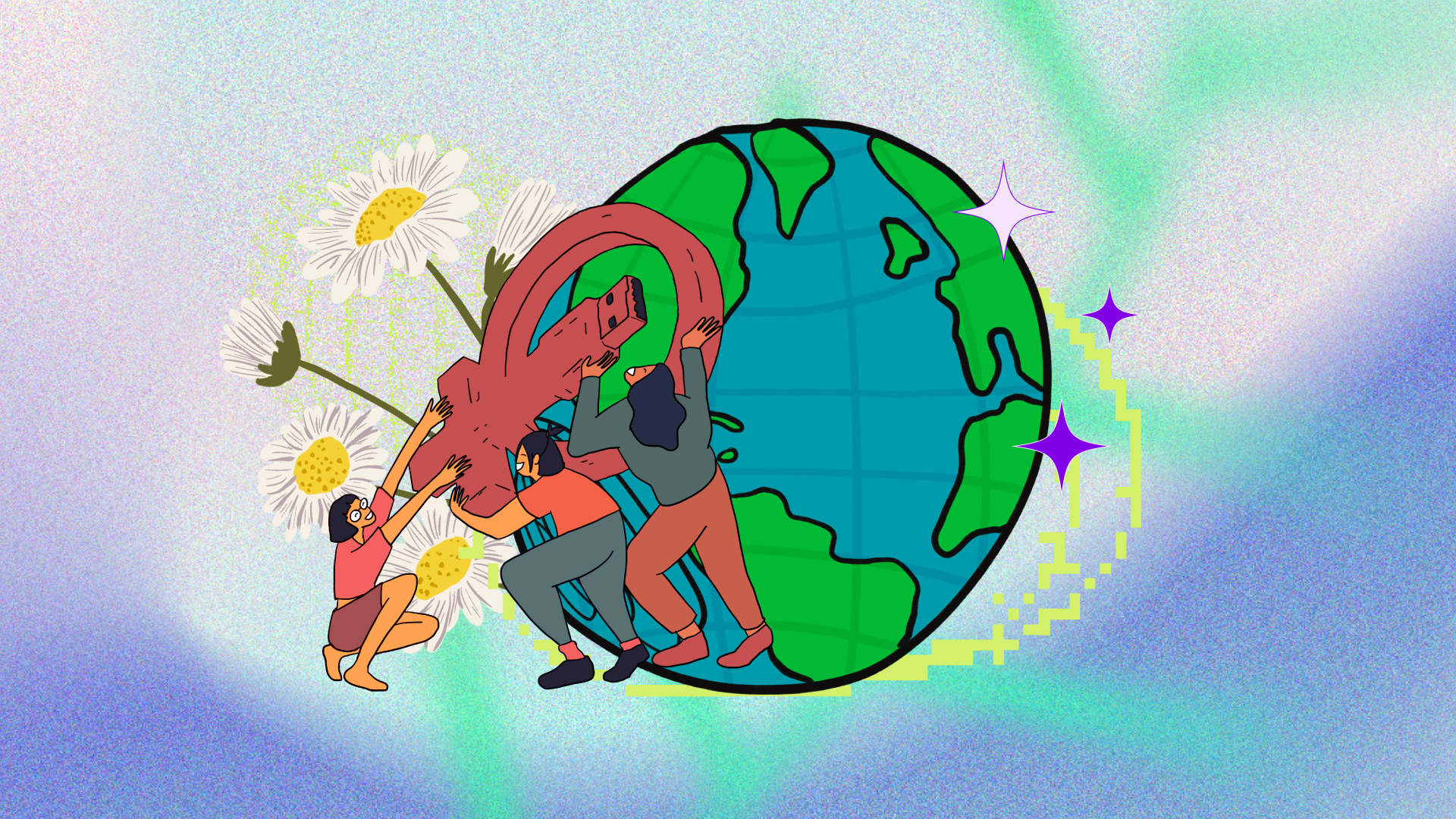Di balik gegap gempita kemajuan teknologi digital—di setiap gawai canggih dan algoritma cerdas yang melekat dengan keseharian hidup kita—terdapat jejak panjang eksploitasi yang nyaris tak pernah kita persoalkan. Dari tambang material langka yang merusak lingkungan dan menyingkirkan komunitas lokal, pusat data raksasa yang menelan energi dalam skala mencengangkan, hingga eksploitasi data pengguna yang menabrak batas etika, pola pengembangan teknologi saat ini dibangun di atas pengabaian sistematis terhadap lingkungan dan kehidupan manusia.
Pertanyaannya kini bukan sekadar “sejauh mana kita bisa memajukan teknologi” ataupun “bagaimana caranya memeratakan akses terhadap teknologi”, melainkan: Dapatkah kita mengembangkan pola yang lain? Bisakah sebuah sistem teknologi dirancang bukan hanya untuk kecanggihan, tetapi juga untuk keberlanjutan dan kesetaraan?
Di tengah kecemasan global akan krisis iklim dan ketimpangan, kita butuh lebih dari sekadar inovasi teknis. Kita butuh keberanian untuk memikirkan ulang dari hulu ke hilir. Dari pengembangan, distribusi hingga pascaguna-nya.
Dalam konteks itulah, untuk memperingati Hari Bumi yang jatuh pada 22 April 2025, PurpleCode Collective mengajak komunitas urban merefleksikan dan menginterogasi interkoneksi antara teknologi yang kita nikmati hari ini dengan kelindan persoalan yang mengikutinya. Lokakarya bertajuk “Efek Rumah Kacau: Menginterogasi Interkoneksi Teknologi, Bumi, dan Logika Ekstraksi dari Perspektif Feminis” ini dilakukan secara tatap muka pada Sabtu (26/4) di PurpleCode Collective Space, Jakarta. Acara ini berlangsung dengan partisipasi aktif dari sejumlah individu penggiat isu perempuan, lingkungan dan teknologi informasi, maupun perwakilan lembaga antara lain Pamflet Generasi, Humanis, Sentral Gerakan Buruh Nasional, Save the Children, dan Kolektif Semai.
Lokakarya ini dimulai dengan pemaparan tentang Prinsip Internet Feminis (PIF) atau The Feminist Principles of the Internet, khususnya untuk kluster prinsip lingkungan. PIF merujuk pada seperangkat nilai dan panduan yang bertujuan memastikan bahwa internet dikembangkan, digunakan, dan diatur secara adil, setara, dan memberdayakan bagi perempuan dan kelompok marjinal lainnya. Difasilitasi oleh Association for Progressive Communications (APC), penyusunan dokumennya dimulai pada 2014 di Malaysia dengan melibatkan para penggiat isu feminisme dan internet dari berbagai negara. Di tahun-tahun berikutnya, dokumen ini terus ditinjau dan dilengkapi. Awalnya, ada 17 prinsip yang dibagi ke dalam lima kluster utama yakni akses, gerakan, ekonomi, ekspresi dan perwujudan (embodiment). Belakangan, jumlah kluster bertambah menjadi enam dengan adanya kluster lingkungan, dengan total 18 prinsip.
Kluster lingkungan menjadi fokus pembahasan lokakarya ini. Kluster baru ini masih berupa rancangan awal dan masih akan terus disempurnakan. Prinsip untuk kluster ini difokuskan pada etika perawatan kolektif dalam pengambilan keputusan terkait perancangan, ekstraksi, produksi, konsumsi, dan pembuangan teknologi. Oleh karena itu, dalam lokakarya ini, pembahasan difokuskan pada tiga kelompok besar yakni: desain/perancangan; ekstraksi & produksi; serta konsumsi/penggunaan dan pengelolaan limbah.
Perancangan
Diskusi dalam kelompok ini menyimpulkan bahwa proses perencanaan teknologi digital saat ini berlangsung satu arah dan tidak peduli pada aspek kolektivitas. Atas nama inovasi, kebaruan terus dikejar demi kredit dan hak cipta individual meskipun yang disebut inovasi baru itu kerapkali mengambil unsur-unsur pengetahuan kolektif dan lokal.
Selain itu, teknologi digital dianggap sebagai panacea atau jawaban untuk semua masalah. Penerapannya pun cenderung dilakukan dengan pemaksaan.
Hal itu antara lain bisa dilihat dari program digitalisasi di berbagai sektor layanan publik yang dilakukan tanpa mempertimbangkan ketimpangan akses dan keamanan data pengguna. Akibatnya, proses digitalisasi itu tidak hanya memperlebar ketimpangan struktural yang sebelumnya sudah ada, namun juga menimbulkan berbagai masalah baru terkait keamanan data pengguna.
Dari sisi desain, banyak platform teknologi yang dirancang dengan desain yang manipulatif dan menimbulkan ketergantungan bahkan kecanduan. Waktu yang dihabiskan setiap orang untuk mengakses internet pun terus bertambah. Hal itu sengaja dilakukan untuk mendorong permintaan yang terus menerus terhadap berbagai platform teknologi. Rancangan terbaru harus selalu dimunculkan untuk menjawab suatu masalah yang kerapkali bukan benar-benar suatu masalah.
Pola pengembangan teknologi tersebut dipandang berwatak kolonial. Ini bisa dilihat dari kecenderungan rancangannya yang berhasrat untuk terus mencaplok dan mengekstrasi. Watak semacam itu pula lekat dengan model bisnis produksi teknologi hari ini, yang juga dipadukan dengan kapitalisme ‘rentism’, yakni mengakumulasi kekayaan bukan melalui produksi nilai melainkan kepemilikan dan kontrol atas aset-aset strategis. Jika dahulu aset strategis itu bisa berupa tanah ataupun bangunan, kini di konteks industri teknologi digital aset itu bisa berupa akses, infrastruktur, termasuk informasi dan data pengguna. Pengguna menjadi buruh yang menghasilkan nilai tidak hanya sebagai penyewa atau ‘subscriber’, tetapi juga karena menyumbang data. Banyak platform yang merancang desain antarmukanya sedemikian rupa sehingga menyulikan pengguna untuk berhenti menjadi penyewa atau ‘unsubscribe’.
Berangkat dari pembacaan terhadap situasi perancangan teknologi tersebut, peserta diskusi dalam kelompok ini pun mulai bersama-sama mengimajinasikan pola perancangan teknologi digital alternatif yang berfokus pada kerja perawatan kolektif. Pola itu dibayangkan mungkin terjadi jika prosesnya partisipatoris, yakni melalui pelibatan bermakna dari kelompok-kelompok yang akan turut mengembangkan maupun menggunakannya. Desain teknologi digital itu mesti bisa menghargai kontribusi pihak-pihak yang terlibat serta mengakui memori kolektif terkait pengalaman dan pengetahuan bersama yang memungkinkan hadirnya produk teknologi tersebut. Dengan begitu, yang dikejar bukan lagi pengakuan inovasi individual yang berujung pada monopoli, melainkan kepemilikan dan pengelolaan bersama. Selain itu, teknologi tersebut mesti dirancang secara terbuka dalam arti transparan dan akuntabel sehingga ada ruang diskusi dalam pengembangan dan pemanfaatannya. Ini berlaku mulai dari bagaimana sistem algoritmanya, bagaimana pengelolaan datanya, siapa saja yang terdampak, dan sebagainya.
Ekstraksi dan produksi
Pembahasan dalam sub-prinsip ekstraksi dan produksi menghasilkan sejumlah kesimpulan terkait kondisi terkini tentang kaitan antara produksi teknologi dengan kegiatan ekstraksi. Seperti yang sudah disinggung di atas, pengembangan teknologi membutuhkan bahan-bahan tambang tidak hanya sebagai bahan komponen fisik namun juga sebagai penghasil energi. Di wilayah Indonesia Timur, kini dampak tambang nikel bagi lingkungan dan warga sekitar menjadi sorotan. Demikian juga dengan dampak pembangunan pembangkit listrik di sejumlah wilayah. Mulai dari paparan logam berat di sungai dan laut, longsor, banjir, polusi udara, hingga hilangnya sumber makanan dan mata pencaharian serta munculnya penyakit.
Perempuan dan kelompok minoritas gender kerap kali mengalami dampak berlapis dari kerusakan itu.
Logika ekstraksi yang sangat merusak itu juga dilakukan dalam konteks data. Berbagai platform digital hingga pengembangan kecerdasan buatan (AI) ditopang oleh penambangan data pengguna. Data-data itu diambil tanpa persetujuan yang benar-benar jelasdari pengguna, lalu diolah menjadi data-data statistik yang dianalisis untuk berbagai kepentingan, mulai dari distribusi iklan yang sesuai dengan kecenderungan perilaku pengguna, hingga manipulasi untuk propaganda politik. Pengelola platform tidak benar-benar mau terbuka ketika diminta menunjukkan basis data mereka.
Dari kesimpulan-kesimpulan tersebut, kelompok ini mencoba mengimajinasikan pengembangan teknologi yang tidak ekstraktif. Namun, dengan dominannya pola pengembangan teknologi yang saat ini ada, berimajinasi tentang pola alternatif ternyata tidak mudah untuk dilakukan.
Oleh karena itu, ada beberapa hal yang bisa dilakukan, yakni terus menerus mendiskusikan adanya logika ekstraktif dalam pengembangan teknologi dan dampaknya bagi lingkungan serta manusia, sembari terus menggali kemungkinan-kemungkinan praktik pengembangan teknologi yang berbasis komunitas dan tidak merusak lingkungan. Beberapa inisiatif bisa menjadi titik berangkat, misalnya pengembangan panel listrik tenaga surya oleh komunitas, pengembangan tower internet berbasis komunitas, dan sebagainya. Selain itu, perlu ada diskusi terus menerus soal definisi teknologi agar pemaknaan kata ini tidak dikuasai pihak tertentu.
Konsumsi
Diskusi dalam kelompok ini difokuskan pada pertanyaan: Apakah konsumen bisa kritis dan peduli?
Ada sejumlah refleksi yang muncul dalam upaya menjawab pertanyaan tersebut. Teknologi selama ini selalu diasosiasikan sebagai sesuatu yang maju, canggih dan cepat. Maka, teknologi harus terus diperbarui secepat mungkin tanpa ada yang benar-benar bertanya apakah perubahan yang cepat itu sungguh-sungguh dibutuhkan. Mengapa teknologi harus berkembang dengan cepat ketika sampai saat ini masih ada wilayah-wilayah yang tidak tersambung ke internet dan warga yang tinggal di dalamnya tetap bisa hidup dengan layak?
Di sisi lain, perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak teknologi sangatlah minim. Dalam konteks mobil listrik, misalnya, pemerintah menggelar karpet merah untuk mempermulus peningkatan konsumsi kendaraan listrik: mulai dari subsidi listrik untuk pemilik kendaraan listrik, bebas biaya pajak, bebas peraturan ganjil genap di Jakarta, dan sebagainya. Kebijakan itu dikeluarkan dengan mengabaikan dampak meningkatnya konsumsi listrik—yang saat ini mayoritas ditopang batu bara—bagi lingkungan dan manusia.
Ditambah lagi dengan adanya semacam jebakan bagi konsumen untuk terus membeli produk baru agar tidak ketinggalan. Perangkat seperti telepon seluler, misalnya, terus dikembangkan dengan fitur dan model terbaru sehingga membuat perangkat dengan fitur lama menjadi ‘ketinggalan jaman’ dan bahkan tidak bisa dipakai secara maksinal. Konsumen mau tidak mau harus mengikuti perkembangan produk terbaru itu jika tidak ingin tertinggal, yang pada akhirnya berdampak pada konsumsi tinggi yang berujung pada masalah sampah elektronik. Hingga saat ini, diskusi tentang pengelolaan limbah dan sampah elektronik kurang terdengar gaungnya.
Sementara itu, para pengembang perangkat digital tidak dituntut untuk bertanggung jawab mengelola limbah dan sampah dari produk yang sudah mereka hasilkan.
Berbagai refleksi tersebut harus dipertimbangkan ketika kita menuntut kondumen untuk bersikap kritis. Artinya, untuk melahirkan konsumen teknologi yang kritis, perlu ada ekosistem yang memungkinkan sikap kritis itu bisa berkembang. Saat ini, ekosistem semacam itu belumlah memadai. Memang ada upaya untuk menciptakan produk yang lebih ramah. Namun, produk-produk yang diberi label ramah lingkungan, peduli pada perempuan, maupun kelompok termarginalkan kerapkali justru dijual dengan harga lebih. Dalam logika ini, menjadi konsumen kritis berarti menjadi konsumen yang mau membayar lebih. Solusi semacam ini dipandang sebagai solusi semu yang bias kelas.
Dari diskusi terebut, muncul beberapa imajinasi tentang apa yang bisa dilakukan untuk mendorong konsumen teknologi yang kritis. Pertama, memperbanyak ruang diskusi untuk membangun kritisismen konsumen. Kedua, mendorong ekosistem yang bisa ‘memaksa’ hadirnya perubahan perilaku konsumen. Keberhasilan kampanye global untuk memboikot produk pendukung invasi Israel atas Palestina, misalnya, bisa menjadi inspirasi untuk menggagas seruan boikot produk teknologi yang merusak lingkungan. Ketiga, mendorong pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan yang mendukung keberlanjutan teknologi dan lingkungan, serta pengembang teknologi untuk bertanggungjawab dalam mengelola limbah dan sampah dari produknya.
Berbagai refleksi dan kesimpulan yang dihasilkan dalam lokakarya ini menunjukkan bahwa ada begitu banyak persoalan di balik pengembangan teknologi digital yang begitu masif.