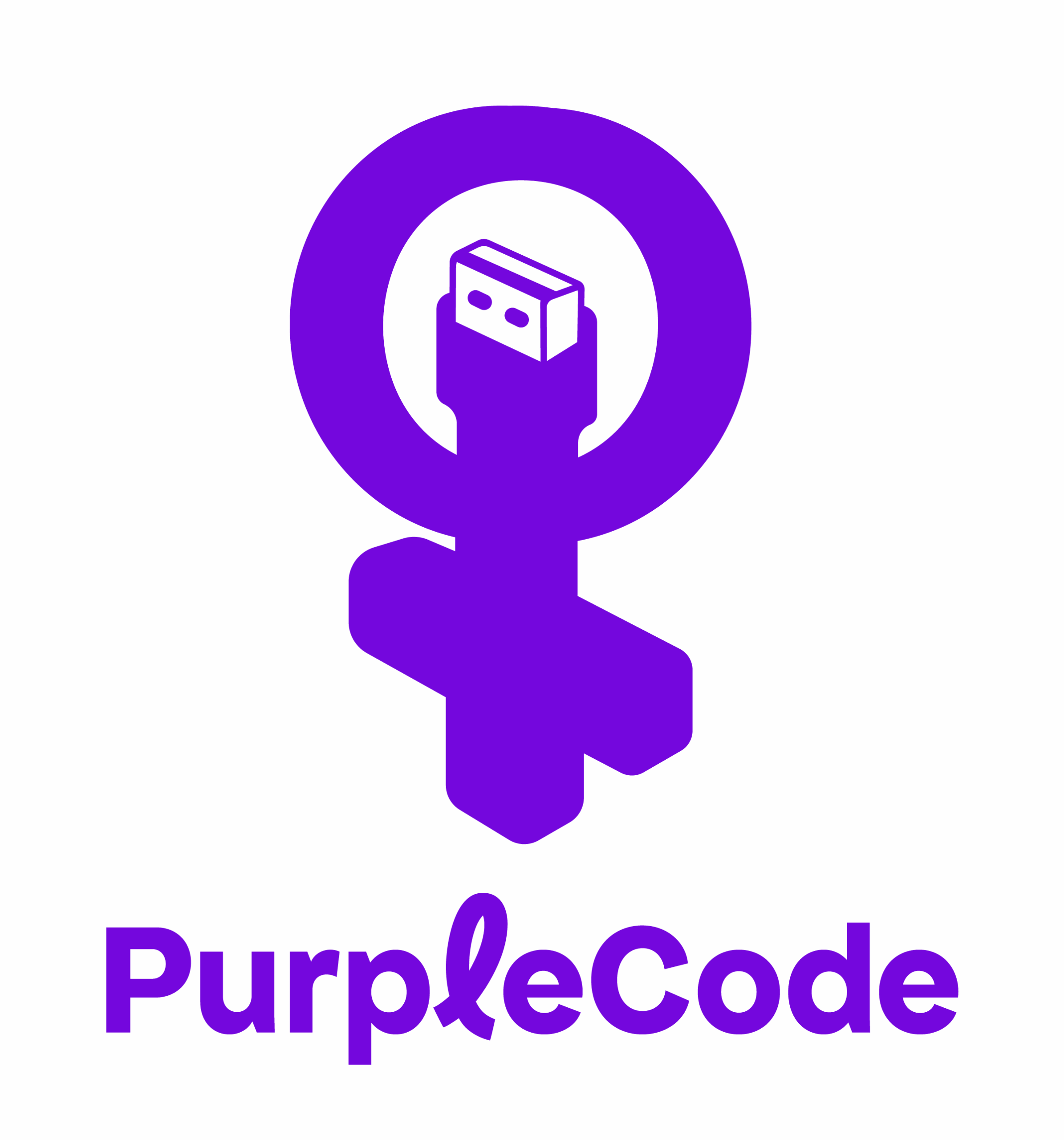“Di akhir hari, aku menyadari semua orang yang membaca berita ini gila, tidaklah waras. Baik yang menyelamatiku; yang mengutukku; yang mengenalku tetapi membaca namaku tanpa beban; yang tidak mengenalku dan menganggap kejadian itu angin lalu; yang mengedit tulisan dengan namaku di dalamnya; yang merupakan bagian dari media itu”.
Kutipan tersebut adalah salah satu bagian dari cerita pendek apik berjudul “Aku Masuk Berita” karya Yuviniar Ekawati. Cerpen tersebut menggambarkan bagaimana media berperan sebagai mesin yang memproduksi kekerasan kepada penyintas kekerasan.
“Aku Masuk Berita” merupakan autofiksi, atau sebuah fiksi yang berangkat dari pengalaman pribadi Yuvi. Yuvi mengisahkan tentang seorang mahasiswi yang sempat mengalami kekerasan dari orang asing di sekitar kampusnya. Tak lama kemudian, seorang jurnalis mewawancarainya, mengeksploitasi kisah si mahasiswi tanpa izin yang jelas, serta mempublikasikan nama mahasiswi tersebut di media.
“Tidak adanya consent yang jelas dalam melakukan wawancara; consent yang tidak transparan; dan lainnya adalah pelanggaran atas hak-hak penyintas. Itu adalah bentuk kekerasan,” ujar Yuvi.
Setelah mengumpulkan keberanian si mahasiswi menyampaikan komplain ke editor naskah tersebut. Alih-alih ditangani sesuai etika jurnalistik, editor tersebut justru melemparkan kesalahan tersebut kepada jurnalisnya.
Apa yang dilakukan oleh media terhadap mahasiswi tersebut bukanlah hal baru. Tulisan Yuvi membuat pengalaman saya dan banyak penyintas lainnya terasa lebih valid. Banyak penyintas yang mengelami kekerasan berlapis dari tindakan media.
Media menjadi ruang di mana kekerasan—berupa eksploitasi kisah penyintas—terjadi. Para petinggi media—yang seharusnya mampu bekerja untuk menyaring mana naskah yang bermasalah dan tidak—menjadi pelaku yang mempertahankan struktur agar kekerasan terus hidup.
***
Pendidikan jurnalistik dan diskusi seputar peran jurnalis lebih banyak membahas bagaimana jurnalis berada di posisi yang rentan untuk mendapatkan kekerasan. Jurnalis sering berhadapan dengan orang-orang yang memiliki kekuasaan dan posisi kuat. Adanya ketidakseimbangan kekuasaan atau relasi kuasa antara jurnalis dengan narasumber membuat mereka rentan mendapatkan kekerasan.
Namun melihat jurnalis sebagai pihak yang selalu berada di posisi rentan bisa menjadi masalah. Dalam liputan konflik, trauma, dan kekerasan, jurnalis justru berada pada posisi yang terbalik. Jurnalis dihadapkan oleh orang dalam situasi rentan di mana jurnalis mampu untuk mengeksploitasi atau menambah lapisan kekerasan yang mereka alami.
Jurnalis bisa memublikasikan kisah penyintas kekerasan secara tidak sensitif tanpa harus menghadapi konsekuensi apa pun; meninggalkan penyintas dengan trauma berlapisnya sendiri, dari situasi psikologis hingga ekonominya. Bahkan, menempatkan penyintas dalam posisi yang berbahaya. Lantas, siapa yang bertanggung jawab atas masalah tersebut?
Orang-orang yang memilki posisi pengambil keputusan di perusahaan media. Orang-orang yang namanya hampir tak pernah disebut setiap permasalahan ini muncul.
Mereka idealnya memahami relasi kuasa. Mengetahui kapan saat jurnalisnya rentan untuk mengalami kekerasan dan kapan saat mereka justru rentan untuk melakukan kekerasan. Mereka seharusnya bisa memastikan jurnalisnya bekerja sesuai etika; memastikan adanya edukasi ke jurnalis soal relasi kuasa, soal kekerasan.
Namun, lagi-lagi, yang lebih banyak terjadi adalah mereka tak mau bertanggung jawab, sebagaimana yang dilakukan oleh editor dalam kisah Yuvi.
Sebetulnya, sudah banyak pihak yang mengkritik masalah ini, mulai dari Komnas Perempuan, hingga lembaga riset independen, seperti Remotivi.
Melalui AJI, para jurnalis juga berkali-kali menyuarakan masalah ini. AJI mencoba mengintervensinya lewat sejumlah cara, mulai dari pemberian edukasi ke jurnalis, hingga mendorong Dewan Pers membuat pedoman liputan kekerasan seksual.
Lantas, mengapa masalah ini masih terus berulang?
Salah satu yang menghambat penanganan masalah ini adalah sistem kerja eksploitatif yang mengharuskan jurnalis membuat berita sebanyak-banyaknya dalam waktu sesingkat mungkin. Jurnalis tak memiliki banyak waktu untuk menjalankan liputan kekerasan yang sesuai etika di mana mereka menanyakan consent dan menjelaskan konsekuensi dari liputannya, menentukan lokasi yang aman, menyiapkan pertanyaan yang sensitif, dan seterusnya.
Jurnalis kerap tak memiliki waktu untuk melakukan konfirmasi atau verifikasi atas informasi yang mereka terima. Konsekuensi yang sering muncul adalah jurnalis mengutip pernyataan dari polisi tentang kekerasan seksual yang sangat bias, tanpa memverifikasinya ke penyintas.
Dengan sistem kerja yang buruk dan nihilnya pendidikan ke jurnalis, apabila ada berita bermasalah yang terbit, media justru menempatkan kesalahannya pada jurnalis.
Pola yang sering terjadi adalah sebagaimana apa yang dilakukan oleh editor di kisah Yuvi. Petinggi media merasa tak bersalah atas kekerasan yang mereka fasilitasi dan lakukan ke penyintas.
Tak jarang ada kasus di mana jurnalis yang akhirnya menerima caci-maki dan doxing di media sosial akibat naskah yang bias gender atau mengeksploitasi kisah penyintas. Salah satunya adalah yang terjadi pada jurnalis Viva, sementara Viva, sebagai media, sebatas menghapus berita tanpa menyampaikan permintaan maaf.
Tanggung jawab dari setiap tulisan yang terbit adalah tanggung jawab media sebagai perusahaan, sebagai organisasi. Namun penyelesaian yang diambil justru lebih banyak menempatkan kesalahan sebagai masalah individu atau jurnalis.
Satu-satunya media nasional yang pernah mempublikasikan permintaan maaf kepada publik atas eksploitasi kisah penyintas adalah Project Multatuli. Langkah bare minimum tersebut justru mendapatkan respon yang luar biasa positif dan malah memposisikan media tersebut sebagai pihak yang “heroik”.
Solusi yang Bias Gender
Peningkatan kesadaran soal masalah ini selama beberapa tahun terakhir memunculkan sejumlah solusi. Salah satunya adalah intervensi lewat edukasi perspektif gender ke jurnalis, tetapi mayoritas yang mengikuti kelas-kelas tersebut adalah perempuan dan queer. Biasanya media mendelegasikan mereka untuk mengikuti pendidikan peliputan kekerasan seksual, atau mereka dituntut secara sosial untuk berinisiatif mengikutinya. Mayoritas media masih memandang isu kekerasan seksual dianggap sebagai “isu perempuan”.
Langkah tersebut berbenturan dengan sistem kerja media yang kerap melakukan segregasi atau pemisahan berdasarkan gender di internalnya. Perempuan lebih banyak ditempatkan di isu-isu yang dianggap feminin, seperti kesehatan, gaya hidup, anak, dan perempuan. Laki-laki di isu-isu “maskulin”, seperti kriminal, politik, dan hukum.
Akibat segregasi tersebut, banyak jurnalis laki-laki yang harus berhadapan dengan isu kekerasan seksual saat meliput isu kriminal, tetapi mereka tak dibekali informasi yang sama dengan jurnalis perempuan. Media berujung tetap memproduksi berita-berita yang mengeksploitasi kisah kekerasan.
Pelatihan yang hanya diberikan kepada gender tertentu juga menempatkan beban moral atas seluruh publikasi berita tentang kekerasan ada di pundak mereka. Tak jarang saya melihat ketika ada media yang mengeksploitasi berita kekerasan seksual, orang-orang justru mempertanyakan para perempuan dan queer jurnalis yang bekerja di media tersebut. Sekalipun mereka tak mengetahui proses liputan hingga publikasi berita tersebut.
Sekalipun sebetulnya representai perempuan hanyalah 25 persen dari seluruh jurnalis di Indonesia. Mereka sulit untuk mengembangkan karirnya ke posisi pengambil keputusan.
Pelatihan peliputan kekerasan lebih sering diselenggarakan oleh pihak eksternal, bukan media. Dengan itu, pelatihan lebih banyak dilakukan atas dorongan individu dan di luar dari jam kerja.
Solusi ini tentunya menambah beban jurnalis yang dianggap bertanggung jawab atas masalah ini. Terlebih, di kultur patriarki, perempuan masih memiliki beban kerja lainnya di luar dari karir, seperti beban domestik atau mengurus anak. Di tengah kesibukannya tersebut, ia masih dituntut untuk menjaga agar medianya benar-benar menjalankan etika saat meliput kekerasan seksual.
Perjalanan pembenahan masalah ini tentunya masih panjang, terlebih dengan kultur dari industri media yang sangat maskulin dan dikemudi oleh boys club atau “abang-abangan”.
Setidaknya kita perlu tahu siapa yang harus ditunjuk dan dituntut untuk menyelesaikan masalah ini. Mereka yang berada di posisi pucuk media; posisi untuk mengambil keputusan dan mengubah sistem kerja jurnalis.
Kita juga perlu menyadari bahwa ini bukanlah permasalahan individu atau sekadar dari jurnalisnya saja, tetapi hasil dari buruknya sistem kerja media daring.